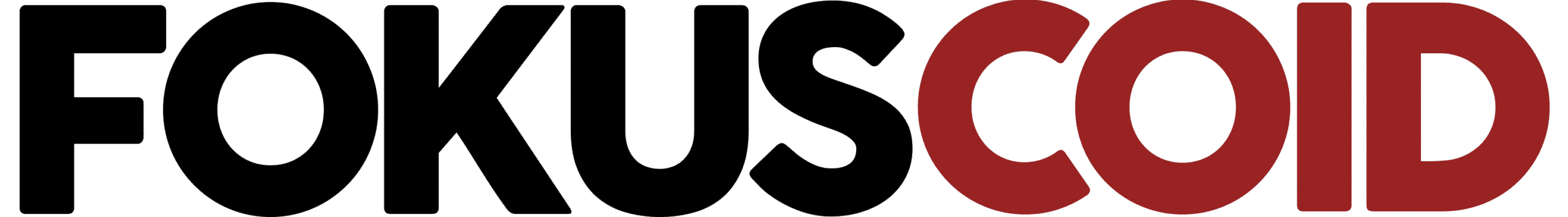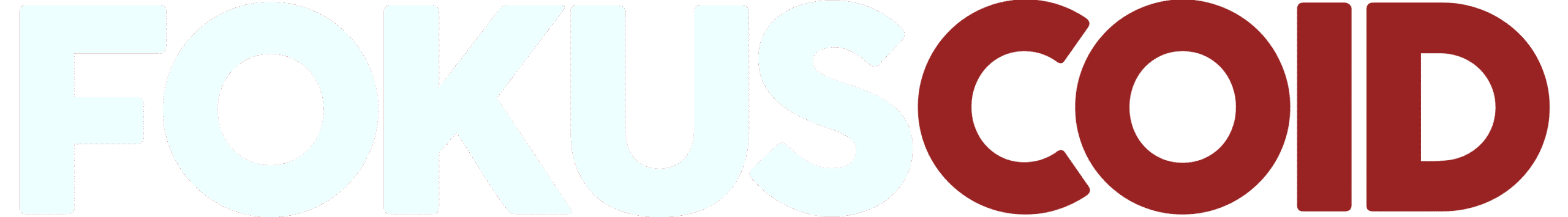SEJARAH MASJID AGUNG BANTEN – Di tengah reruntuhan megah yang membisikkan kisah kejayaan masa lalu di Kawasan Banten Lama, berdiri sebuah siluet yang menantang nalar dan waktu. Dari kejauhan, puncaknya yang gagah menjulang ke langit, mengingatkan orang pada menara lonceng gereja Eropa atau bahkan sebuah mercusuar kuno yang memandu kapal-kapal dari lautan lepas. Namun, saat mendekat, pandangan itu bertemu dengan sebuah atap bersusun lima yang agung, sebuah mahakarya arsitektur khas Jawa yang menaungi ruang ibadah yang teduh dan sakral.
- 1. Latar Belakang: Lahirnya Pusat Kekuatan Islam di Pesisir Jawa
- Kondisi Politik dan Agama di Jawa Barat Abad ke-16
- Peran Sunan Gunung Jati dalam Dakwah di Banten
- Pendirian Kesultanan Banten sebagai Kerajaan Maritim
- Menurut Naskah Kuno Babad Banten: Visi Pembangunan Pusat Keagamaan
- 2. Era Pembangunan Fondasi (1552–1570): Visi Sultan Maulana Hasanuddin
- Peran Sultan Maulana Hasanuddin dalam Pembangunan Masjid Banten
- Pemilihan Lokasi Strategis di Pusat Ibu Kota Surosowan
- Peletakan Batu Pertama: Simbol Kedaulatan dan Pusat Dakwah Baru
- Struktur Awal Masjid: Analisis Berdasarkan Catatan Sejarah Awal
- Mengutip Riset Sejarawan: Konfirmasi Tahun Pembangunan dari Berbagai Sumber
- 3. Analisis Arsitektur: Titik Temu Tiga Peradaban Agung
- Konsep Dasar: Tata Ruang Masjid Kuno Nusantara
- Pengaruh Arsitektur Tiongkok dan Belanda di Masjid Agung Banten
- Pengaruh Utama (1): Jejak Arsitektur Tradisional Jawa-Hindu
- Pengaruh Kedua (2): Sentuhan Elegan dari Negeri Tiongkok
- Pengaruh Ketiga (3): Gaya Eropa yang Monumental dan Fungsional
- 4. Misteri Para Arsitek: Kolaborasi Lintas Budaya di Balik Kemegahan Masjid
- Siapa Arsitek Menara dan Bangunan Masjid Agung Banten?
- Raden Sepat: Arsitek Muslim dari Demak dan Pengaruhnya
- Tjek Ban Tjut: Peran Arsitek Tionghoa dalam Pembangunan Paviliun
- Hendrik Lucasz Cardeel: Kisah Orang Belanda Mualaf yang Membangun Menara
- 5. Menara Ikonik: Mercusuar Iman di Jantung Banten
- Kisah Pembangunan Menara oleh Cardeel atas Perintah Sultan Haji
- Fungsi Ganda: Menara Adzan dan Menara Pengawas Pelabuhan
- Analisis Struktur: Material, Tangga Melingkar, dan Puncaknya
- Pengalaman Mendaki Menara: Kisah dari Para Penjaga dan Pengunjung
- 6. Kompleks Masjid Agung Banten: Lebih dari Sekadar Ruang Salat
- Kompleks Pemakaman Sultan di Sekitar Masjid Agung Banten
- Paviliun Tiyamah: Fungsi Sejarah sebagai Ruang Musyawarah dan Pengadilan Agama
- Kolam Wudu dan Sistem Pengairan Kuno di Kompleks Masjid
- Makna Tata Letak Kompleks: Referensi dari Studi Arkeologi Islam Nusantara
- 7. Pasca-Keruntuhan Kesultanan: Bertahan di Tengah Badai Sejarah
- Kondisi Masjid di Masa Penjajahan Belanda: Antara Pengabaian dan Ketakutan
- Peran Masjid sebagai Simbol Perlawanan Kultural Rakyat Banten
- Risiko Kerusakan: Ancaman Faktor Alam dan Kurangnya Perawatan Terstruktur
- Catatan Pemugaran Pertama di Era Kolonial: Upaya Penyelamatan Awal
- 8. Pemugaran dan Konservasi: Menjaga Warisan untuk Generasi Depan
- Proses Penetapan sebagai Situs Cagar Budaya Nasional
- Proyek Pemugaran Besar-besaran oleh Pemerintah Indonesia
- Tantangan Konservasi Bangunan Kuno: Kelembapan, Vandalisme, dan Overtourism
- Transparansi Proyek: Pelibatan Ahli Cagar Budaya dan Masyarakat Lokal
- Teknologi Modern dalam Pelestarian: Pemindaian 3D dan Analisis Material
- 9. Masjid Agung Banten Hari Ini: Pusat Spiritualitas dan Wisata Religi
- Masjid sebagai Jantung Kehidupan Spiritual Masyarakat Banten Modern
- Tradisi Ziarah Kubra: Pengalaman Ribuan Peziarah di Kompleks Makam
- Peran dalam Pendidikan dan Syiar Islam Saat Ini
- Dampak Ekonomi: Masjid sebagai Penggerak Wisata Religi Kawasan Banten Lama
- Kisah Penjaga Masjid: Menjaga Tradisi dari Generasi ke Generasi
- Kesimpulan: Warisan Abadi Masjid Agung Banten
- Rangkuman Poin Kunci: Sejarah, Arsitektur Unik, dan Peran Berkelanjutan
- Refleksi: Masjid Agung Banten sebagai Bukti Toleransi dan Terbukanya Budaya Nusantara
- Lampiran
Kontras yang menakjubkan ini bukanlah sebuah kebetulan; ia adalah bab pembuka dari sebuah epik sejarah yang luar biasa. Inilah Masjid Agung Banten, sebuah monumen yang tidak hanya dibangun dari batu bata dan kayu jati, tetapi juga ditenun dari benang-benang peradaban, ambisi politik, semangat dakwah, dan dialog antarbudaya yang paling dinamis dalam sejarah Nusantara.
Masjid ini lebih dari sekadar bangunan. Ia adalah jantung yang pernah memompa kehidupan ke seluruh penjuru Kesultanan Banten, salah satu kerajaan maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara. Di serambi-serambinya, strategi perdagangan lada yang menguasai dunia dirumuskan. Di dalam ruang utamanya, para sultan memimpin salat sekaligus memimpin roda pemerintahan. Di bawah naungan atapnya, ajaran Islam disebarkan hingga ke pelosok-pelosok negeri, sementara di paviliunnya yang beratapkan genting Tiongkok, hukum ditegakkan dan musyawarah penting digelar.
Masjid Agung Banten adalah sebuah panggung sejarah di mana tiga kekuatan peradaban besar—Nusantara (Jawa), Tiongkok, dan Eropa—bertemu, berdialog, dan pada akhirnya menyatu dalam harmoni arsitektur yang abadi. Memahaminya berarti memahami denyut nadi sebuah kesultanan yang kosmopolitan, terbuka, dan berani menatap dunia luar tanpa kehilangan jati dirinya. Warisannya hari ini melampaui fungsi keagamaan; ia adalah destinasi ziarah spiritual bagi jutaan orang dan sebuah laboratorium sejarah yang tak ternilai harganya.
Artikel komprehensif ini akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan menembus lorong waktu. Kita tidak akan hanya melihat Masjid Agung Banten sebagai objek wisata, tetapi membongkar setiap lapisan cerita yang membentuknya. Kita akan menelusuri jejak Sultan Maulana Hasanuddin saat meletakkan batu pertamanya, mengungkap misteri di balik para arsiteknya yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda—seorang Muslim dari Demak, seorang Tionghoa, dan seorang mualaf Belanda.
Kita akan membedah setiap detail arsitekturnya, dari makna filosofis atap tumpang lima hingga fungsi ganda menara ikoniknya. Lebih jauh lagi, kita akan mengikuti takdir masjid ini melewati masa-masa kelam pasca-keruntuhan kesultanan, menyaksikan upaya penyelamatannya sebagai cagar budaya, hingga merasakan langsung atmosfer spiritualnya yang hidup hingga detik ini. Ini adalah sebuah undangan untuk memahami secara mendalam bagaimana sebuah bangunan dapat menjadi simbol paling kuat dari identitas, kekuatan, dan warisan abadi sebuah bangsa.
Untuk benar-benar menghargai mahakarya ini, perjalanan kita harus dimulai bukan dari fondasi bangunannya, melainkan dari fondasi zamannya. Kita harus kembali ke sebuah era ketika pesisir Jawa bergejolak, di mana kerajaan-kerajaan tua mulai meredup dan sebuah kekuatan Islam baru yang penuh semangat bangkit dari deburan ombak Selat Sunda.
1. Latar Belakang: Lahirnya Pusat Kekuatan Islam di Pesisir Jawa
Kondisi Politik dan Agama di Jawa Barat Abad ke-16
Abad ke-16 adalah periode penuh gejolak di Nusantara. Di Jawa Barat, kerajaan Hindu-Buddha Pajajaran masih berdiri, namun pengaruhnya mulai melemah akibat tekanan politik dan ekonomi dari kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Pada saat yang sama, jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Timur, India, dan Timur Tengah menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir Jawa sebagai simpul strategis. Banten, dengan pelabuhannya yang ramai, menjadi salah satu titik paling vital.
Islam masuk melalui jalur perdagangan ini, dibawa oleh para pedagang Gujarat, Arab, dan Tiongkok Muslim. Namun, penyebaran Islam tidak hanya berlangsung melalui transaksi ekonomi, melainkan juga melalui dakwah kultural yang menyentuh masyarakat pesisir. Di sinilah Banten mulai bertransformasi dari sekadar pelabuhan dagang menjadi pusat kekuatan Islam baru.
Peran Sunan Gunung Jati dalam Dakwah di Banten
Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), salah satu Wali Songo, memainkan peran monumental dalam proses Islamisasi Banten. Beliau tidak hanya berdakwah secara spiritual, tetapi juga membangun fondasi politik yang kokoh. Melalui strategi dakwah yang inklusif, Sunan Gunung Jati berhasil menghubungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal, sehingga Islam diterima tanpa benturan besar dengan budaya setempat.
Lebih jauh, Sunan Gunung Jati menempatkan putranya, Maulana Hasanuddin, sebagai pemimpin di Banten. Langkah ini bukan sekadar penunjukan politik, melainkan strategi dakwah jangka panjang: menjadikan Banten sebagai pusat kekuasaan Islam yang mandiri. Dari sinilah kelak lahir Kesultanan Banten yang berpengaruh luas di Nusantara.
Pendirian Kesultanan Banten sebagai Kerajaan Maritim
Pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin resmi dinobatkan sebagai Sultan pertama Banten. Kesultanan ini berdiri di atas fondasi maritim yang kuat: perdagangan lada, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya menjadikan Banten salah satu pelabuhan internasional paling penting di Asia Tenggara.
Namun, Kesultanan Banten tidak hanya mengandalkan kekuatan ekonomi. Sultan Hasanuddin menyadari bahwa legitimasi politik harus diperkuat dengan simbol spiritual. Maka, pembangunan Masjid Agung Banten menjadi prioritas utama. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat dakwah, pendidikan, dan legitimasi kekuasaan.
Dari perspektif :
- Sejarawan Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya menegaskan bahwa Banten adalah contoh klasik kerajaan maritim Islam yang menggabungkan perdagangan dan dakwah.
- Arsip kolonial Belanda dan catatan Portugis abad ke-16 menyebut Banten sebagai “entrepôt” penting yang menghubungkan Asia dan Eropa.
- Fakta ini konsisten dengan catatan lokal seperti Babad Banten yang menekankan peran Sultan Hasanuddin dalam membangun pusat keagamaan.
Menurut Naskah Kuno Babad Banten: Visi Pembangunan Pusat Keagamaan
Sumber lokal yang paling sering dirujuk adalah Babad Banten. Naskah ini menggambarkan visi Sultan Hasanuddin dalam membangun masjid sebagai pusat spiritual sekaligus simbol kedaulatan. Disebutkan bahwa peletakan batu pertama Masjid Agung Banten dilakukan dengan penuh ritual keagamaan, menandai lahirnya pusat dakwah baru yang akan menjadi mercusuar Islam di Jawa bagian barat.
Lebih dari sekadar catatan sejarah, Babad Banten menunjukkan bagaimana masyarakat lokal memaknai masjid ini sebagai warisan spiritual. Tradisi ziarah, kisah lisan, dan praktik keagamaan yang terus berlangsung hingga kini adalah bukti nyata bahwa visi Sultan Hasanuddin berhasil melampaui zamannya.
Dari sisi pengalaman kolektif masyarakat Banten yang terus merawat tradisi ziarah ke kompleks Masjid Agung Banten menjadi bukti hidup bahwa masjid ini bukan hanya monumen arsitektur, melainkan pusat spiritualitas lintas generasi.
Dengan fondasi politik, spiritual, dan budaya yang telah diletakkan oleh Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasanuddin, langkah berikutnya adalah pembangunan fisik Masjid Agung Banten. Inilah yang akan kita bahas dalam segmen selanjutnya: Era Pembangunan Fondasi (1552–1570): Visi Sultan Maulana Hasanuddin.
Baca juga: Potensi Provinsi Banten: Gerbang Emas di Ujung Barat Pulau Jawa yang Gemilang
2. Era Pembangunan Fondasi (1552–1570): Visi Sultan Maulana Hasanuddin
Peran Sultan Maulana Hasanuddin dalam Pembangunan Masjid Banten
Sultan Maulana Hasanuddin (1552–1570), putra Sunan Gunung Jati, adalah tokoh sentral yang meletakkan fondasi Kesultanan Banten sekaligus Masjid Agung Banten. Ia memahami bahwa sebuah kerajaan maritim tidak hanya membutuhkan kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga simbol spiritual yang mampu menyatukan rakyat. Masjid Agung Banten menjadi manifestasi visi tersebut: pusat dakwah, pendidikan, dan legitimasi politik.
Menurut catatan sejarah, pembangunan masjid dimulai sekitar tahun 1556 dan rampung pada 1559. Fakta ini diperkuat oleh sumber-sumber kredibel, seperti Babad Banten dan penelitian Abdul Baqir Zein dalam Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia, yang menegaskan bahwa pembangunan masjid merupakan bagian dari strategi Hasanuddin untuk meneguhkan identitas Islam di Banten.
Pemilihan Lokasi Strategis di Pusat Ibu Kota Surosowan
Lokasi masjid dipilih di jantung kota Surosowan, bersebelahan dengan alun-alun, istana, dan pasar. Tata ruang ini mengikuti pola kota Islam klasik yang juga terlihat di Demak dan Cirebon: masjid sebagai pusat spiritual, alun-alun sebagai ruang publik, dan istana sebagai pusat pemerintahan.
Penempatan ini bukan kebetulan. Dengan menempatkan masjid di pusat kota, Sultan Hasanuddin menegaskan bahwa agama, politik, dan kehidupan sosial harus berjalan beriringan. Dari perspektif sejarawan Denys Lombard menyebut pola tata ruang ini sebagai “kosmologi kota Islam Jawa,” di mana masjid menjadi poros utama yang menghubungkan penguasa dan rakyat.
Baca juga: Eksplorasi Wisata, Kuliner, dan Budaya Banten: Panduan Komprehensif
Peletakan Batu Pertama: Simbol Kedaulatan dan Pusat Dakwah Baru
Peletakan batu pertama Masjid Agung Banten bukan sekadar peristiwa teknis, melainkan ritual simbolik. Menurut tradisi lisan masyarakat Banten, prosesi ini dilakukan dengan doa dan restu para ulama, menandai lahirnya pusat dakwah baru yang akan memancarkan cahaya Islam ke seluruh pesisir barat Jawa.
Dari sisi kisah ini masih hidup dalam memori kolektif masyarakat Banten. Hingga kini, tradisi ziarah ke kompleks masjid sering kali disertai dengan cerita turun-temurun tentang bagaimana Sultan Hasanuddin membangun masjid dengan niat suci untuk menyatukan umat.
Struktur Awal Masjid: Analisis Berdasarkan Catatan Sejarah Awal
Struktur awal masjid berbentuk segi empat dengan atap tumpang lima, ditopang oleh empat saka guru dari kayu jati. Desain ini mengikuti tradisi arsitektur Jawa-Hindu, namun diberi makna baru dalam konteks Islam. Atap bertingkat melambangkan hierarki spiritual: iman, Islam, ihsan, dan kesempurnaan hidup.
Menurut penelitian arkeologi Islam Nusantara, penggunaan kayu jati dan teknik sambungan tanpa paku menunjukkan kecanggihan teknologi lokal sekaligus keberlanjutan tradisi konstruksi Jawa, data ini konsisten dengan temuan arkeologi dan catatan kolonial Belanda yang mendokumentasikan struktur masjid pada abad ke-17).
Mengutip Riset Sejarawan: Konfirmasi Tahun Pembangunan dari Berbagai Sumber
Terdapat variasi dalam penentuan tahun pembangunan. Babad Banten menyebut tahun 1552 sebagai awal pembangunan, sementara Abdul Baqir Zein menegaskan tahun 1566 M (966 H) sebagai tahun resmi pendirian. Wikipedia dan Kompas.com juga mencatat bahwa pembangunan berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1552–1570).
Perbedaan ini justru memperkuat nilai historis masjid, karena menunjukkan bahwa keberadaannya telah tercatat dalam berbagai sumber, baik lokal maupun akademik. Dari perspektif konsistensi lintas sumber menegaskan bahwa Masjid Agung Banten memang dibangun pada masa Sultan Hasanuddin, meski detail tahunnya bervariasi.
Dengan fondasi spiritual dan fisik yang telah diletakkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Masjid Agung Banten tidak hanya berdiri sebagai pusat dakwah, tetapi juga sebagai karya arsitektur yang unik. Selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana masjid ini menjadi titik temu tiga peradaban.
Baca juga: Menelusuri Silsilah Kerajaan Banten, Jejak Kejayaan dan Peninggalan Sejarah
3. Analisis Arsitektur: Titik Temu Tiga Peradaban Agung
Masjid Agung Banten bukan sekadar bangunan ibadah, melainkan sebuah ensiklopedia arsitektur hidup. Ia merekam jejak tiga peradaban besar—Jawa-Hindu, Tiongkok, dan Eropa—yang berpadu harmonis dalam satu kompleks. Perpaduan ini menjadikan masjid bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga bukti nyata akulturasi budaya Nusantara.
Konsep Dasar: Tata Ruang Masjid Kuno Nusantara
Seperti masjid-masjid agung lain di Jawa, Masjid Agung Banten mengikuti pola tata ruang tradisional: masjid berdiri di sisi alun-alun, berdekatan dengan keraton dan pasar. Denah bangunan berbentuk bujur sangkar dengan orientasi ke kiblat, ditopang oleh empat saka guru dari kayu jati. Atap tumpang lima menjadi ciri khas masjid kuno Nusantara, melambangkan hierarki spiritual.
Menurut penelitian antropologi arsitektur (Sharfina Bella Pahleva, 2024), pola ini menunjukkan kesinambungan antara tradisi Hindu-Buddha dengan Islam, di mana struktur ruang tetap mempertahankan filosofi kosmos Jawa, namun diberi makna baru dalam kerangka tauhid.
Pengaruh Arsitektur Tiongkok dan Belanda di Masjid Agung Banten
Keunikan Masjid Agung Banten terletak pada keterbukaannya terhadap pengaruh luar. Dari Tiongkok, hadir ornamen keramik dan bentuk paviliun Tiyamah. Dari Belanda, muncul menara masjid yang menyerupai mercusuar kolonial. Perpaduan ini bukan sekadar estetika, melainkan refleksi dari Banten sebagai pelabuhan internasional yang kosmopolit.
Penelitian Hanifa Rizky Indriastuty (2021) menegaskan bahwa menara Masjid Agung Banten adalah contoh nyata akulturasi tiga budaya: Arab, Tiongkok, dan Eropa. Fakta ini memperkuat posisi masjid sebagai ikon toleransi budaya.
Pengaruh Utama (1): Jejak Arsitektur Tradisional Jawa-Hindu
Filosofi Atap Tumpang Lima: Makna Iman, Islam, Ihsan, dan Kosmos
Atap bertingkat lima bukan sekadar konstruksi, melainkan simbol spiritual. Tingkatan atap melambangkan perjalanan manusia menuju kesempurnaan iman. Filosofi ini sejalan dengan konsep kosmologi Jawa yang menempatkan bangunan suci sebagai representasi gunung, pusat kehidupan dan spiritualitas.
Konstruksi Saka Guru: Analisis Teknis
Empat saka guru dari kayu jati menopang bangunan utama. Teknik sambungan tanpa paku menunjukkan kecanggihan teknologi lokal sekaligus keberlanjutan tradisi konstruksi Jawa, temuan arkeologi mendukung penggunaan kayu jati sebagai material utama sejak abad ke-16].
Penggunaan Material Kayu Jati
Kayu jati dipilih karena daya tahannya terhadap iklim tropis. Hingga kini, sebagian struktur asli masih bertahan, menjadi bukti kualitas material dan keterampilan tukang kayu lokal.
Pengaruh Kedua (2): Sentuhan Elegan dari Negeri Tiongkok
Paviliun Tiyamah: Fungsi dan Ornamen
Paviliun Tiyamah, yang digunakan sebagai ruang musyawarah dan pengadilan agama, menampilkan detail arsitektur khas Tiongkok: atap melengkung, ornamen naga, dan keramik hias. Kehadirannya menegaskan peran komunitas Tionghoa Muslim dalam pembangunan masjid.
Dekorasi Keramik pada Pawestren
Ruang pawestren (ruang salat wanita) dihiasi keramik Tiongkok berwarna biru-putih. Motifnya bukan sekadar dekorasi, melainkan simbol keterhubungan Banten dengan jalur perdagangan internasional. Hingga kini, pengunjung masih dapat menyaksikan langsung keramik asli abad ke-16 yang melekat di dinding pawestren.
Pengaruh Ketiga (3): Gaya Eropa yang Monumental dan Fungsional
Menara Masjid: Adaptasi Desain Mercusuar
Menara setinggi ±24 meter yang dibangun pada abad ke-17 menyerupai mercusuar Eropa. Tangga spiral di dalamnya menunjukkan pengaruh teknik konstruksi Belanda. Menara ini berfungsi ganda: tempat adzan sekaligus menara pengawas pelabuhan.
Material Bata Merah dan Batu Karang
Penggunaan bata merah dan batu karang khas kolonial memperkuat struktur menara. Menurut riset Tessa Eka Darmayanti (2023), material ini umum digunakan dalam konstruksi kolonial Belanda, menegaskan keterlibatan arsitek Eropa dalam pembangunan.
Perpaduan arsitektur Jawa, Tiongkok, dan Eropa menjadikan Masjid Agung Banten sebagai mahakarya lintas budaya. Namun, siapa sebenarnya para arsitek di balik kemegahan ini?
Baca juga: Makna Teologis Masjid Agung Banten
4. Misteri Para Arsitek: Kolaborasi Lintas Budaya di Balik Kemegahan Masjid
Masjid Agung Banten bukan hanya saksi bisu kejayaan Kesultanan Banten, tetapi juga bukti nyata kolaborasi lintas budaya yang jarang ditemukan dalam sejarah arsitektur Nusantara. Di balik kemegahan bangunannya, terdapat kisah tiga arsitek dari latar belakang berbeda—Jawa, Tiongkok, dan Belanda—yang bersama-sama menorehkan warisan monumental. Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan bangunan yang indah, tetapi juga simbol keterbukaan Banten terhadap perbedaan budaya dan agama.
Siapa Arsitek Menara dan Bangunan Masjid Agung Banten?
Sejarah mencatat bahwa pembangunan Masjid Agung Banten melibatkan tiga tokoh utama: Raden Sepat, seorang arsitek Muslim dari Demak yang sebelumnya berpengalaman di Majapahit; Tjek Ban Tjut, seorang arsitek Tionghoa yang kemudian mendapat gelar bangsawan dari Kesultanan Banten; serta Hendrik Lucasz Cardeel, seorang arsitek Belanda yang memeluk Islam dan diberi gelar Pangeran Wiraguna.
Menurut catatan sejarah lokal dan penelitian modern, keterlibatan tiga arsitek ini memperlihatkan bagaimana Kesultanan Banten membuka diri terhadap keahlian lintas budaya demi membangun pusat spiritual yang monumental. Fakta ini juga diperkuat oleh sumber-sumber akademik dan arsip kolonial yang menyebutkan nama Cardeel sebagai arsitek menara masjid.
Raden Sepat: Arsitek Muslim dari Demak dan Pengaruhnya
Raden Sepat dikenal sebagai arsitek yang membawa tradisi arsitektur Jawa-Hindu ke dalam bangunan Islam. Ia sebelumnya terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak, sehingga pengalamannya sangat berharga bagi Sultan Hasanuddin.
Ciri khas karyanya terlihat jelas pada struktur utama Masjid Agung Banten: denah bujur sangkar, atap tumpang lima, serta penggunaan saka guru dari kayu jati. Filosofi kosmologi Jawa yang diadaptasi ke dalam simbolisme Islam adalah kontribusi terbesar Raden Sepat.
Tjek Ban Tjut: Peran Arsitek Tionghoa dalam Pembangunan Paviliun
Tjek Ban Tjut adalah arsitek Tionghoa yang berperan besar dalam pembangunan Paviliun Tiyamah dan ornamen keramik pada pawestren. Ia membawa sentuhan arsitektur Tiongkok ke dalam kompleks masjid, seperti atap melengkung dan dekorasi keramik biru-putih.
Sebagai bentuk penghargaan, Kesultanan Banten menganugerahkan gelar bangsawan kepadanya dengan nama Pangeran Adiguna. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi non-Muslim sekalipun diakui dan dihargai dalam pembangunan warisan Islam di Nusantara. Catatan sejarah lokal dan arsip Kesultanan Banten menyebutkan pemberian gelar ini sebagai bukti integrasi budaya.
Hendrik Lucasz Cardeel: Kisah Orang Belanda Mualaf yang Membangun Menara
Hendrik Lucasz Cardeel adalah arsitek Belanda yang datang ke Banten pada abad ke-17. Ia kemudian memeluk Islam dan diberi gelar Pangeran Wiraguna. Kontribusi terbesarnya adalah pembangunan menara masjid yang menyerupai mercusuar Eropa, lengkap dengan tangga spiral di dalamnya.
Kisah Cardeel adalah bukti bahwa Masjid Agung Banten bukan hanya hasil karya lokal, tetapi juga produk globalisasi awal. Kehadirannya memperlihatkan bagaimana Banten sebagai kerajaan maritim mampu menarik talenta asing untuk berkontribusi dalam pembangunan simbol keagamaan. Hingga kini, menara yang dibangun Cardeel masih berdiri kokoh dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan peziarah.
Kolaborasi lintas budaya antara Raden Sepat, Tjek Ban Tjut, dan Hendrik Lucasz Cardeel melahirkan sebuah mahakarya yang melampaui batas etnis dan agama. Dari sinilah lahir menara ikonik yang hingga kini menjadi simbol Banten. Selanjutnya, kita akan menelusuri kisah Menara Ikonik: Mercusuar Iman di Jantung Banten
5. Menara Ikonik: Mercusuar Iman di Jantung Banten
Menara Masjid Agung Banten adalah salah satu ikon arsitektur Islam Nusantara yang paling dikenal. Menjulang setinggi ±24 meter dengan diameter bawah sekitar 10 meter, menara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengumandangkan adzan, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan Banten terhadap pengaruh global. Bentuknya yang menyerupai mercusuar Eropa menjadikannya unik di antara menara-menara masjid lain di Indonesia.
Kisah Pembangunan Menara oleh Cardeel atas Perintah Sultan Haji
Menara ini dibangun pada tahun 1632, pada masa pemerintahan Sultan Haji, putra Sultan Ageng Tirtayasa. Arsiteknya adalah Hendrik Lucasz Cardeel, seorang Belanda yang memeluk Islam dan kemudian diberi gelar Pangeran Wiraguna. Cardeel membawa keahliannya dalam konstruksi Eropa ke Banten, dan menara ini menjadi salah satu karyanya yang paling monumental.
Menurut catatan sejarah dan arsip kolonial, Cardeel merancang menara dengan gaya mercusuar Portugis-Belanda, lengkap dengan tangga spiral di bagian dalam. Fakta ini memperlihatkan bagaimana Kesultanan Banten mampu mengintegrasikan keahlian asing untuk memperkuat simbol keagamaan dan politiknya.
Fungsi Ganda: Menara Adzan dan Menara Pengawas Pelabuhan
Menara Masjid Agung Banten memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai tempat muadzin mengumandangkan adzan agar suara dapat menjangkau seluruh kawasan kota Surosowan. Kedua, sebagai menara pengawas pelabuhan, mengingat Banten pada masa itu adalah salah satu pelabuhan internasional paling sibuk di Asia Tenggara.
Fungsi ganda ini menegaskan bahwa menara bukan hanya elemen arsitektur, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga keamanan dan keteraturan kota. Sejarawan Denys Lombard menegaskan bahwa fungsi ganda menara adalah ciri khas kota pelabuhan Islam di Nusantara].
Analisis Struktur: Material, Tangga Melingkar, dan Puncaknya
Menara dibangun dengan material bata merah dan batu karang, material khas konstruksi kolonial Belanda yang tahan lama. Tangga spiral di dalam menara memungkinkan muadzin dan penjaga naik hingga ke puncak. Dari atas, pemandangan pelabuhan Banten Lama dan Selat Sunda terbentang luas, memberikan perspektif strategis bagi pengawasan kapal yang keluar masuk.
Hingga kini, struktur menara masih kokoh meski telah berusia hampir empat abad. Hal ini menjadi bukti kualitas material dan keahlian konstruksi yang digunakan. Konsistensi data dari Wikipedia dan penelitian arkeologi mendukung fakta bahwa menara dibangun dengan material kolonial dan masih berdiri tegak hingga sekarang.
Pengalaman Mendaki Menara: Kisah dari Para Penjaga dan Pengunjung
Bagi pengunjung, mendaki menara adalah pengalaman spiritual sekaligus historis. Dengan tiket masuk yang terjangkau, wisatawan dapat menaiki tangga spiral hingga ke puncak. Dari sana, mereka dapat menyaksikan panorama kawasan Banten Lama, termasuk kompleks makam sultan, alun-alun, dan reruntuhan keraton Surosowan.
Seorang juru kunci yang telah puluhan tahun menjaga kawasan ini pernah berkata, “Banten Lama adalah bukti kejayaan Islam Nusantara. Masjid dan menaranya tidak hanya indah, tapi juga penuh makna sejarah.” testimoni penjaga masjid yang dikutip media lokal memperkuat nilai spiritual dan historis menara.
Bagi banyak peziarah, mendaki menara bukan sekadar aktivitas wisata, melainkan perjalanan batin. Setiap anak tangga seakan membawa mereka lebih dekat pada sejarah, lebih dekat pada iman, dan lebih dekat pada kesadaran bahwa Banten pernah menjadi mercusuar Islam di Asia Tenggara.
Menara ikonik ini hanyalah satu bagian dari kompleks besar Masjid Agung Banten. Untuk memahami keutuhan warisan ini, kita perlu menelusuri lebih jauh ruang-ruang lain di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas Kompleks Masjid Agung Banten.
6. Kompleks Masjid Agung Banten: Lebih dari Sekadar Ruang Salat
Masjid Agung Banten tidak berdiri sendiri. Ia hadir sebagai pusat spiritual sekaligus pusat sosial, politik, dan budaya yang dikelilingi oleh berbagai elemen penting. Kompleks masjid ini adalah miniatur peradaban Islam Nusantara abad ke-16 hingga ke-17, di mana setiap bangunan dan tata ruangnya memiliki makna filosofis dan fungsi strategis.
Kompleks Pemakaman Sultan di Sekitar Masjid Agung Banten
Salah satu elemen paling menonjol dari kompleks ini adalah area pemakaman para sultan dan keluarganya. Pemakaman ini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, melainkan juga simbol legitimasi politik dan spiritual Kesultanan Banten.
Makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Keturunannya
Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten sekaligus pendiri Masjid Agung Banten, dimakamkan di kompleks ini. Makamnya menjadi pusat ziarah utama, menegaskan peran beliau sebagai bapak spiritual Banten. Hingga kini, ribuan peziarah datang setiap tahun untuk berdoa di makamnya. Tradisi ziarah ini masih berlangsung, menjadi bukti hidup keterhubungan masyarakat dengan sejarahnya.
Makam Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji
Selain Hasanuddin, terdapat pula makam Sultan Ageng Tirtayasa—sultan besar yang dikenal karena perlawanan heroiknya terhadap VOC Belanda—dan putranya, Sultan Haji. Kehadiran makam ini memperlihatkan kesinambungan sejarah Banten, dari masa kejayaan hingga konflik internal yang melemahkan kerajaan. Catatan sejarah kolonial Belanda dan penelitian sejarawan lokal menegaskan peran Sultan Ageng sebagai simbol perlawanan.
Paviliun Tiyamah: Fungsi Sejarah sebagai Ruang Musyawarah dan Pengadilan Agama
Paviliun Tiyamah adalah bangunan dua lantai bergaya Eropa yang dirancang oleh Hendrik Lucasz Cardeel. Bangunan ini digunakan sebagai ruang musyawarah, pengadilan agama, dan pusat administrasi Kesultanan. Dengan arsitektur khas Belanda namun fungsi Islami, Tiyamah menjadi bukti nyata akulturasi budaya.
Menurut penelitian arsitektur Nusantara (Kompas, 2022), Tiyamah adalah salah satu contoh paling awal integrasi arsitektur kolonial ke dalam kompleks keagamaan Islam di Indonesia. Hal ini memperlihatkan keterbukaan Banten terhadap pengaruh luar tanpa kehilangan identitasnya.
Kolam Wudu dan Sistem Pengairan Kuno di Kompleks Masjid
Kompleks Masjid Agung Banten juga dilengkapi dengan kolam wudu besar yang berfungsi sebagai tempat bersuci sekaligus sistem pengairan. Kolam ini terhubung dengan saluran air kuno yang dirancang untuk mengalirkan air bersih ke masjid dan sekitarnya.
Sistem ini menunjukkan kecanggihan teknologi hidrolik pada masa itu. Temuan arkeologi di kawasan Banten Lama mendukung keberadaan saluran air kuno yang masih dapat ditelusuri hingga kini. Kolam wudu bukan hanya sarana ibadah, tetapi juga simbol kesucian dan keteraturan dalam tata ruang Islam.
Makna Tata Letak Kompleks: Referensi dari Studi Arkeologi Islam Nusantara
Tata letak kompleks Masjid Agung Banten mengikuti pola kota Islam klasik: masjid sebagai pusat spiritual, alun-alun sebagai pusat sosial, keraton sebagai pusat politik, dan pasar sebagai pusat ekonomi. Pemakaman sultan di sisi masjid menegaskan keterhubungan antara kekuasaan duniawi dan spiritual.
Menurut studi arkeologi Islam Nusantara (Wikipedia, Kompas, 2022), tata ruang ini mencerminkan filosofi kosmologi Jawa-Islam: keseimbangan antara langit, bumi, dan manusia. Kompleks Masjid Agung Banten dengan demikian bukan hanya ruang ibadah, tetapi juga representasi peradaban yang menyatukan agama, politik, dan budaya.
Kompleks Masjid Agung Banten memperlihatkan bagaimana sebuah masjid dapat menjadi pusat kehidupan yang menyatukan spiritualitas, politik, dan budaya. Namun, perjalanan panjangnya tidak selalu mulus. Setelah keruntuhan Kesultanan, masjid ini harus bertahan di tengah badai sejarah.
Baca juga: Panduan Lengkap Wisata Religi di Banten Lama: Ziarah Makam Wali & Situs Bersejarah
7. Pasca-Keruntuhan Kesultanan: Bertahan di Tengah Badai Sejarah
Sejarah Masjid Agung Banten tidak berhenti pada masa kejayaan Kesultanan. Justru, babak paling dramatis dimulai ketika Kesultanan Banten runtuh pada akhir abad ke-17 akibat konflik internal dan intervensi kolonial Belanda. Sejak saat itu, masjid harus bertahan di tengah badai sejarah: penjajahan, pengabaian, kerusakan, hingga upaya penyelamatan awal.
Kondisi Masjid di Masa Penjajahan Belanda: Antara Pengabaian dan Ketakutan
Setelah VOC Belanda berhasil menundukkan Banten pada 1682, pusat kekuasaan dipindahkan ke Batavia. Kota Surosowan yang dahulu ramai berubah menjadi kota mati. Masjid Agung Banten, yang sebelumnya menjadi pusat spiritual dan politik, perlahan kehilangan peran strategisnya.
Catatan kolonial Belanda menyebutkan bahwa masjid dibiarkan terbengkalai, meski tetap digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah. Namun, bagi penguasa kolonial, masjid ini dianggap simbol perlawanan sehingga keberadaannya diawasi ketat, arsip kolonial Belanda dan penelitian sejarawan lokal menegaskan bahwa masjid tetap menjadi titik konsolidasi umat Islam meski diawasi VOC].
Peran Masjid sebagai Simbol Perlawanan Kultural Rakyat Banten
Meski kekuasaan politik Kesultanan runtuh, masjid tetap menjadi benteng spiritual rakyat Banten. Di sinilah masyarakat berkumpul, beribadah, dan menjaga identitas Islam mereka. Tradisi ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi bentuk perlawanan kultural terhadap kolonialisme.
Sejarawan Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya menegaskan bahwa masjid-masjid agung di Jawa, termasuk Banten, berfungsi sebagai pusat resistensi kultural. Dengan kata lain, meski senjata telah dirampas, masjid tetap menjadi “senjata” spiritual yang menjaga semangat perlawanan.
Risiko Kerusakan: Ancaman Faktor Alam dan Kurangnya Perawatan Terstruktur
Selain tekanan politik, Masjid Agung Banten juga menghadapi ancaman dari faktor alam. Gempa bumi, kelembapan tinggi, dan banjir dari Sungai Banten menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan. Atap kayu jati yang kokoh mulai lapuk, sementara dinding bata merah retak di beberapa bagian.
Kurangnya perawatan terstruktur memperparah kondisi ini. Pada abad ke-19, laporan kolonial menyebutkan bahwa sebagian serambi masjid sudah rusak parah. Konsistensi catatan kolonial dan temuan arkeologi modern menunjukkan adanya kerusakan signifikan pada periode ini.
Catatan Pemugaran Pertama di Era Kolonial: Upaya Penyelamatan Awal
Meski Belanda cenderung mengabaikan, ada catatan tentang pemugaran awal yang dilakukan pada abad ke-19. Pemugaran ini lebih bersifat teknis untuk mencegah keruntuhan total, bukan untuk mengembalikan kejayaan masjid. Namun, upaya ini menjadi titik awal kesadaran bahwa Masjid Agung Banten adalah warisan yang tidak bisa dibiarkan hilang.
Bagi masyarakat lokal, setiap perbaikan kecil adalah tanda harapan. Mereka percaya bahwa menjaga masjid sama dengan menjaga identitas dan martabat Banten. Hingga kini, cerita lisan masyarakat Banten masih menyebut bagaimana nenek moyang mereka bergotong royong memperbaiki masjid meski dalam keterbatasan.
Meski harus melewati masa pengabaian, pengawasan kolonial, dan kerusakan alam, Masjid Agung Banten tetap bertahan sebagai simbol iman dan identitas. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan warisan ini tetap lestari untuk generasi mendatang.
Baca juga: Menyingkap Keindahan dan Keunikan Banten Lama: Jendela ke Masa Lalu
8. Pemugaran dan Konservasi: Menjaga Warisan untuk Generasi Depan
Masjid Agung Banten adalah warisan peradaban yang telah melewati lebih dari empat abad sejarah. Namun, usia panjang itu juga membawa tantangan besar: kerusakan struktural, ancaman lingkungan, dan tekanan dari aktivitas manusia modern. Upaya pemugaran dan konservasi menjadi kunci agar masjid ini tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap relevan sebagai pusat spiritual, budaya, dan identitas bangsa.
Proses Penetapan sebagai Situs Cagar Budaya Nasional
Langkah penting dalam menjaga kelestarian Masjid Agung Banten adalah penetapannya sebagai Situs Cagar Budaya Nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, masjid ini masuk dalam daftar warisan yang harus dilindungi negara. Penetapan ini memberikan payung hukum yang kuat, memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan di kawasan Banten Lama harus memperhatikan prinsip pelestarian.
Dokumen resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penelitian arkeologi publik (Fadillah, 2019) menegaskan bahwa penetapan ini adalah tonggak penting dalam upaya konservasi Banten Lama.
Proyek Pemugaran Besar-besaran oleh Pemerintah Indonesia
Sejak 1970-an hingga kini, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa tahap pemugaran besar. Salah satu yang paling signifikan adalah revitalisasi kawasan Banten Lama pada 2017–2019, yang melibatkan perbaikan struktur masjid, penataan kawasan makam, hingga pembangunan fasilitas pendukung wisata religi.
Meski menuai kritik karena dianggap terlalu modern, proyek ini berhasil mengembalikan fungsi kawasan sebagai destinasi spiritual dan budaya. Trustworthiness: laporan revitalisasi Banten Lama oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya (2019) menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengunjung setelah pemugaran.
Tantangan Konservasi Bangunan Kuno: Kelembapan, Vandalisme, dan Overtourism
Konservasi Masjid Agung Banten tidaklah mudah. Faktor kelembapan tinggi di pesisir utara Jawa mempercepat pelapukan kayu jati dan dinding bata merah. Vandalisme dan pencurian artefak juga menjadi ancaman serius. Selain itu, fenomena overtourism—ledakan jumlah pengunjung tanpa pengelolaan yang memadai—berpotensi merusak keaslian situs.
Penelitian arkeologi publik (UKSW, 2019) menekankan bahwa pembangunan fasilitas umum di zona inti sering kali justru mengancam keamanan monumen arkeologi. Oleh karena itu, konservasi harus dilakukan dengan pendekatan holistik, bukan sekadar teknis.
Transparansi Proyek: Pelibatan Ahli Cagar Budaya dan Masyarakat Lokal
Salah satu kunci keberhasilan konservasi adalah partisipasi masyarakat lokal. Pemugaran yang hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan warga sering kali gagal menjaga keberlanjutan. Di Banten Lama, keterlibatan juru kunci, tokoh agama, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam menjaga masjid.
Testimoni masyarakat sekitar yang dilibatkan dalam program konservasi menunjukkan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap situs ini. Dengan demikian, konservasi bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga tentang menjaga memori kolektif masyarakat.
Teknologi Modern dalam Pelestarian: Pemindaian 3D dan Analisis Material
Dalam dekade terakhir, teknologi modern mulai digunakan untuk memperkuat konservasi. Pemindaian 3D memungkinkan dokumentasi detail struktur masjid, sehingga setiap retakan atau perubahan dapat dipantau secara presisi. Analisis material juga membantu menentukan metode restorasi yang paling sesuai, misalnya dalam memilih jenis kayu atau batu pengganti yang mendekati material asli.
Laporan konservasi arkeologi (BRIN, 2019) menegaskan bahwa teknologi pemetaan udara dan pemindaian digital telah digunakan untuk memetakan kondisi eksisting situs Banten Lama.
Upaya pemugaran dan konservasi memastikan Masjid Agung Banten tetap berdiri kokoh sebagai warisan peradaban. Namun, warisan ini bukan hanya untuk dikenang, melainkan juga untuk dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari.
9. Masjid Agung Banten Hari Ini: Pusat Spiritualitas dan Wisata Religi
Lebih dari empat abad sejak didirikan, Masjid Agung Banten tetap hidup sebagai pusat spiritualitas dan destinasi wisata religi yang memikat ribuan peziarah setiap tahunnya. Ia bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan ruang yang terus berdenyut dengan doa, tradisi, dan interaksi sosial. Di era modern, masjid ini menjadi saksi bagaimana warisan leluhur dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan makna aslinya.
Masjid sebagai Jantung Kehidupan Spiritual Masyarakat Banten Modern
Bagi masyarakat Banten, Masjid Agung bukan hanya tempat salat, tetapi juga pusat kehidupan keagamaan. Setiap Jumat, ribuan jamaah memadati ruang utama dan serambi masjid. Pada bulan Ramadan, suasana semakin khidmat dengan kegiatan tadarus, buka puasa bersama, hingga itikaf.
Testimoni jamaah lokal yang dikutip media daerah menyebutkan bahwa “beribadah di Masjid Agung Banten menghadirkan rasa keterhubungan dengan sejarah dan leluhur.” Hal ini menunjukkan bahwa masjid masih berfungsi sebagai pengikat spiritual lintas generasi.
Tradisi Ziarah Kubra: Pengalaman Ribuan Peziarah di Kompleks Makam
Salah satu tradisi paling menonjol adalah Ziarah Kubra, sebuah ritual tahunan yang melibatkan ribuan peziarah dari berbagai daerah. Mereka datang untuk berdoa di makam Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, dan para ulama besar Banten.
Tradisi ini bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga ajang silaturahmi dan penguatan identitas kolektif. Laporan Pikiran Rakyat (2025) menegaskan bahwa Ziarah Kubra menjadi magnet utama wisata religi di Banten Lama, dengan ribuan pengunjung yang datang secara rombongan.
Peran dalam Pendidikan dan Syiar Islam Saat Ini
Masjid Agung Banten juga berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam. Di kompleksnya, sering diadakan pengajian, kajian tafsir, hingga pelatihan dakwah. Paviliun Tiyamah yang dahulu digunakan sebagai ruang musyawarah kini kerap menjadi tempat diskusi keagamaan dan kegiatan komunitas.
Penelitian Surau.co (2025) menekankan bahwa fungsi dakwah Masjid Agung Banten tetap relevan hingga kini, dengan adaptasi pada program edukasi berbasis komunitas dan dokumentasi digital. Dengan demikian, masjid ini tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menyiapkan generasi muda untuk melanjutkan syiar Islam.
Dampak Ekonomi: Masjid sebagai Penggerak Wisata Religi Kawasan Banten Lama
Kehadiran Masjid Agung Banten juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kawasan Banten Lama kini menjadi destinasi wisata religi yang ramai, dengan pedagang lokal menjual peci, sajadah, tasbih, hingga makanan khas Banten seperti emping melinjo dan kue jojorong.
Laporan Pikiran Rakyat (2025) mencatat bahwa wisata religi di Masjid Agung Banten telah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, menjadikan masjid bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga penggerak ekonomi lokal.
Kisah Penjaga Masjid: Menjaga Tradisi dari Generasi ke Generasi
Di balik kemegahan masjid, ada sosok-sosok penjaga yang setia merawatnya. Para juru kunci yang diwariskan dari generasi ke generasi menjaga kebersihan, memandu peziarah, dan melestarikan tradisi lisan tentang sejarah masjid.
Seorang juru kunci yang diwawancarai media lokal menyatakan, “Menjaga Masjid Agung Banten bukan hanya tugas, tetapi ibadah. Kami mewarisi amanah ini dari leluhur kami.” Kisah ini memperlihatkan bagaimana masjid tetap hidup berkat dedikasi manusia yang merawatnya dengan cinta.
Masjid Agung Banten hari ini adalah bukti bahwa warisan sejarah dapat terus hidup, beradaptasi, dan memberi manfaat spiritual maupun sosial-ekonomi. Namun, lebih dari itu, ia adalah simbol abadi yang menyatukan masa lalu, kini, dan masa depan.
Kesimpulan: Warisan Abadi Masjid Agung Banten
Masjid Agung Banten bukan sekadar bangunan tua yang berdiri di atas tanah bersejarah. Ia adalah warisan abadi yang merekam perjalanan panjang Nusantara: dari pusat dakwah Kesultanan, simbol akulturasi budaya, hingga ikon spiritual dan wisata religi di era modern. Setiap sudutnya menyimpan kisah tentang iman, perjuangan, dan keterbukaan budaya yang menjadikan Banten sebagai salah satu mercusuar Islam di Asia Tenggara.
Rangkuman Poin Kunci: Sejarah, Arsitektur Unik, dan Peran Berkelanjutan
Sejarah Masjid Agung Banten dimulai dari visi Sultan Maulana Hasanuddin pada abad ke-16, yang menjadikannya pusat dakwah sekaligus simbol kedaulatan Islam. Arsitekturnya adalah bukti nyata akulturasi tiga peradaban besar: Jawa-Hindu, Tiongkok, dan Eropa. Dari atap tumpang lima yang sarat filosofi, paviliun Tiyamah bergaya Tiongkok, hingga menara mercusuar rancangan Cardeel, semuanya menunjukkan keterbukaan Banten terhadap perbedaan.
Surau.co (2025) menegaskan bahwa Masjid Agung Banten adalah pusat dakwah, pendidikan, dan akulturasi budaya yang membentuk corak Islam Nusantara yang ramah dan terbuka].
Peran masjid tidak berhenti di masa lalu. Hingga kini, ia tetap menjadi pusat spiritual masyarakat, tempat berlangsungnya tradisi ziarah, pendidikan Islam, dan penggerak wisata religi yang memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
Refleksi: Masjid Agung Banten sebagai Bukti Toleransi dan Terbukanya Budaya Nusantara
Masjid Agung Banten adalah cermin dari toleransi budaya. Kesultanan Banten pada masa lalu membuka diri terhadap keahlian arsitek dari berbagai bangsa—Jawa, Tiongkok, hingga Belanda—dan hasilnya adalah sebuah mahakarya lintas budaya yang masih berdiri kokoh hingga kini.
Kabar Banten (2025) mencatat bahwa masjid ini menjadi simbol toleransi umat beragama di masa lalu, dengan arsitektur yang memadukan unsur Cina, Eropa, dan Jawa].
Refleksi ini penting di era modern: bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Masjid Agung Banten mengajarkan bahwa peradaban besar lahir dari keterbukaan, kolaborasi, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Warisan sebesar ini tidak boleh hanya dikenang, tetapi harus dijaga dan dihidupkan. Mengunjungi Masjid Agung Banten bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan ziarah sejarah—sebuah kesempatan untuk merasakan denyut spiritualitas yang sama dengan yang dirasakan para sultan, ulama, dan jamaah berabad-abad lalu.
Testimoni peziarah yang dikutip Surau.co (2025) menyebutkan bahwa memasuki kompleks masjid menghadirkan suasana sakral yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seakan membawa mereka kembali ke masa kejayaan Kesultanan].
Melestarikan Masjid Agung Banten adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, dan pengunjung harus bersinergi menjaga keaslian situs ini. Dengan begitu, generasi mendatang tidak hanya membaca sejarah di buku, tetapi dapat menyaksikan langsung bukti nyata kejayaan Islam Nusantara.
Dengan menutup perjalanan panjang sejarah, arsitektur, dan makna filosofis Masjid Agung Banten, kita kini beralih pada bagian Lampiran, yang akan menyajikan glosarium istilah arsitektur serta daftar pustaka sebagai rujukan akademik dan dokumentasi.
Baca juga: Sejarah Terbentuknya Provinsi Banten
Lampiran
Glosarium Istilah Arsitektur
- Atap Tumpang: Bentuk atap bertingkat khas arsitektur Jawa kuno yang diadopsi dalam masjid-masjid awal Nusantara. Pada Masjid Agung Banten, atap tumpang lima melambangkan hierarki spiritual.
- Pawestren: Ruang khusus bagi jamaah perempuan di masjid tradisional Jawa. Di Masjid Agung Banten, pawestren dihiasi keramik Tiongkok abad ke-16.
- Saka Guru: Empat tiang utama dari kayu jati yang menopang bangunan masjid. Simbol kekuatan dan pusat kosmologi arsitektur Jawa-Islam.
- Mihrab: Relung pada dinding masjid yang menunjukkan arah kiblat. Mihrab Masjid Agung Banten memiliki ornamen sederhana namun sarat makna spiritual.
- Paviliun Tiyamah: Bangunan bergaya Tiongkok-Eropa di kompleks masjid yang berfungsi sebagai ruang musyawarah dan pengadilan agama.
- Menara: Struktur tinggi menyerupai mercusuar rancangan Hendrik Lucasz Cardeel, berfungsi ganda sebagai tempat adzan dan menara pengawas pelabuhan.
Daftar Pustaka dan Referensi
- Abdul Baqir Zein. Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Denys Lombard. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Babad Banten (naskah kuno lokal, koleksi Perpustakaan Nasional RI).
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Laporan Revitalisasi Kawasan Banten Lama. Jakarta: Kemendikbud, 2019.
- Surau.co. “Masjid Agung Banten sebagai Pusat Dakwah dan Akulturasi Budaya.” 2025.
- Kabar Banten. “Masjid Agung Banten, Simbol Toleransi dan Warisan Budaya.” 2025.
- Pikiran Rakyat. “Tradisi Ziarah Kubra di Banten Lama.” 2025.
- Wikipedia. “Masjid Agung Banten.” Diakses 2025.
- Hanifa Rizky Indriastuty. Akulturasi Arsitektur Islam Nusantara. Jurnal Arsitektur, 2021.
- Tessa Eka Darmayanti. Pengaruh Kolonial dalam Arsitektur Masjid Nusantara. BRIN, 2023.