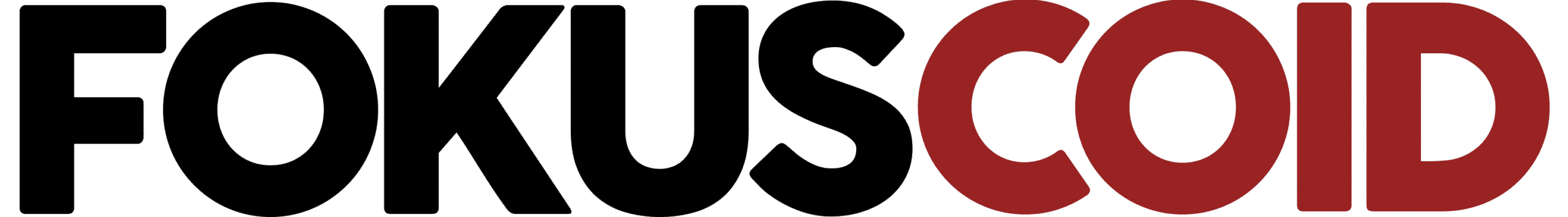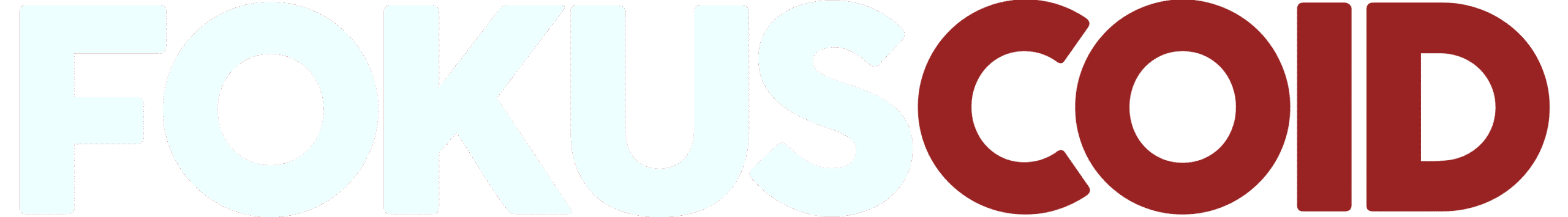Kerajaan Mataram, yang berdiri pada abad ke-16, menerapkan sistem feodalisme yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyatnya. Sistem ini menempatkan kekuasaan sepenuhnya di tangan kaum bangsawan, membuat rakyat kecil tidak berdaya dan harus menerima berbagai bentuk kesengsaraan tanpa bisa melawan.
Feodalisme di Masa Kerajaan Mataram
Pada masa Kerajaan Mataram, undang-undang yang menjadi pedoman hukum berasal dari kitab Manawa. Kitab ini mengatur bahwa “Tanah dan segala isinya adalah milik raja.” Artinya, rakyat tidak memiliki hak milik atas tanah yang mereka tinggali dan garap. Feodalisme juga tercermin dalam struktur sosial yang ketat, di mana kekuasaan dikuasai oleh para bangsawan, sementara rakyat biasa hanyalah pelayan yang bekerja untuk mereka.
Sistem Kelas Sosial yang Kaku
Dalam sistem feodalisme, terdapat hierarki sosial yang jelas dan tidak dapat diubah. Raja berada di puncak kekuasaan, diikuti oleh kelompok Nayaka dan Sentana. Nayaka adalah birokrat kerajaan, sedangkan Sentana adalah keluarga atau orang kepercayaan raja. Mereka tidak digaji dengan uang, melainkan diberikan tanah untuk dikelola. Namun, tanah tersebut tidak menjadi hak milik mereka, melainkan hanya diberikan hak pengelolaan.
Nayaka dan Sentana dinilai berdasarkan jumlah tanah yang mereka terima dari raja. Tanah ini disebut “Cacah.” Pengelolaan tanah ini dilakukan oleh Bekel, yang mengawasi tanah-tanah tersebut dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Untuk menggarap tanah, Bekel merekrut Sikep, yaitu petani bayaran yang bekerja mengelola tanah.
Kehidupan Petani dan Buruh di Bawah Sistem Feodalisme
Sikep adalah petani bayaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah. Mereka bekerja keras menggarap tanah, namun hasil panen mereka sebagian besar harus diserahkan kepada pemilik tanah. Selain itu, mereka juga harus membayar pajak, yang semakin menambah beban hidup mereka.
Di bawah Sikep, terdapat Batur atau Bujang, yaitu pekerja yang membantu Sikep dalam mengelola tanah. Kedua kelompok ini, baik Sikep maupun Batur, tidak pernah menerima gaji yang layak. Mereka hanya diizinkan mengambil sedikit hasil panen untuk makan, sementara sebagian besar hasil kerja mereka diberikan kepada bangsawan dan pejabat kerajaan.
Meskipun hidup mereka penuh dengan penderitaan, para Sikep merasa bangga karena memiliki pekerjaan. Status sebagai Sikep, meski sulit, dianggap lebih baik daripada menggelandang tanpa pekerjaan. Namun, kenyataannya, feodalisme ini hanya memperparah kemiskinan dan penderitaan rakyat.
Analogi Kehidupan Modern
Jika melihat kondisi Sikep dan Batur, kita bisa menemukan kemiripan dengan situasi para pegawai honorer di zaman sekarang. Mereka bekerja keras, tetapi sering kali menerima gaji jauh di bawah standar upah minimum. Para honorer ini tetap bekerja meski gaji mereka tidak sepadan dengan usaha yang mereka lakukan, dan jarang berani melakukan protes karena takut kehilangan pekerjaan.
Begitu pula dengan Batur atau Bujang, yang bisa diibaratkan seperti penyewa pakaian badut untuk mengemis di lampu merah. Mereka hanya bergantung pada belas kasihan orang lain untuk mendapatkan uang, mirip dengan bagaimana rakyat pada masa feodalisme bergantung pada penguasa tanah.
Feodalisme dan Pajak
Kebijakan pajak yang diberlakukan pada masa feodalisme di Kerajaan Mataram juga memiliki kesamaan dengan sistem pajak saat ini. Kita diminta membayar pajak secara rutin, tetapi sering kali tidak tahu ke mana uang pajak tersebut dialokasikan atau apakah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Baca juga:Sejarah dan Ciri-Ciri Feodalisme di Indonesia
Kesimpulan
Sistem feodalisme di masa Kerajaan Mataram jelas-jelas membuat rakyat menderita. Rakyat dipaksa bekerja keras tanpa imbalan yang setara, sementara para bangsawan dan pejabat kerajaan menikmati hasil kerja mereka. Tanpa disadari, budaya feodalisme ini masih ada di masyarakat kita saat ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat kecil dan berusaha menciptakan sistem yang lebih adil dan merata.
Penulis: Ayu Navisatus Saniyah, mahasiswi semester satu prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).