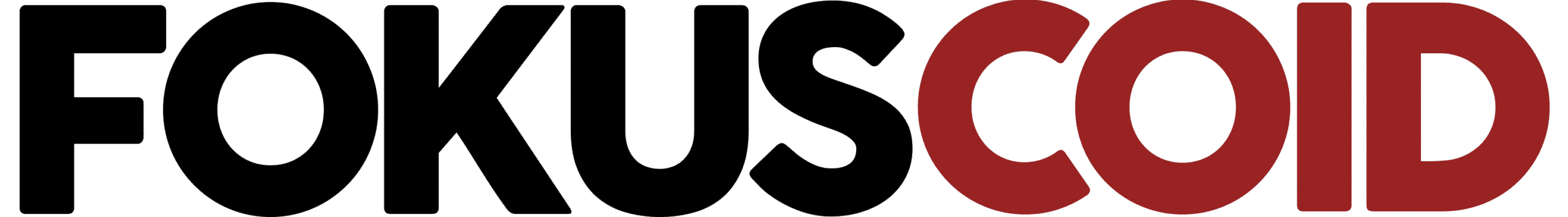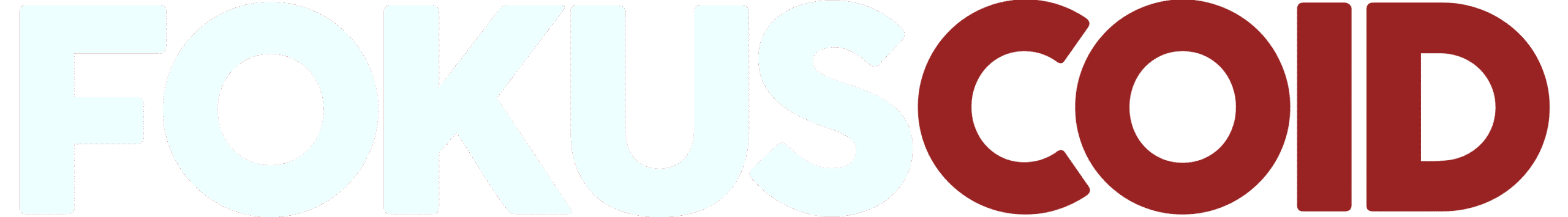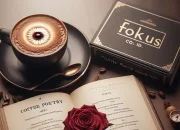FOKUS SEJARAH – Banten dikenal sebagai tanah para jawara, ulama, dan pendekar. Dari masa ke masa, wilayah ini melahirkan tokoh-tokoh tangguh yang disegani karena keberanian dan kebijaksanaannya.
- Mengapa Banten Dijuluki “Tanah Jawara”?
- Era Emas Kesultanan Banten: Poros Perdagangan dan Kekuatan Militer
- Peran Jawara dan Pendekar dalam Struktur Sosial Masyarakat
- Jejak Perlawanan Terhadap VOC
- Catatan Sejarah: Tomé Pires dan Naskah Kuno
- Golok Ciomas: Pusaka Sakral Penjaga Kehormatan Tanah Banten
- Legenda Ki Cengkuk dan Ki Tundung: Asal-usul Golok Sakti “Si Denok”
- Anatomi Golok Ciomas: Gagang, Simpay, Bilah, dan Warangka
- Ciri Khas dan Tuah Golok Ciomas Asli
- Jenis-Jenis Golok Ciomas
- Ritual Penyepuhan dan Gendam: Menghidupkan Bilah
- Golok Sulangkar: Bilah Kembar Simbol Kekuatan dan Kehormatan Bangsawan Banten
- Asal-usul Golok Sulangkar: Dari Istana Kesultanan hingga Warisan Jawara
- Desain Bilah Kembar yang Penuh Filosofi
- Material dan Detail Ukiran Golok Sulangkar
- Fungsi dan Makna Sosial Golok Sulangkar
- Ritual dan Etika Kepemilikan Golok Sulangkar
- Golok Sulangkar di Masa Kini
- Kujang Banten: Dari Alat Pertanian Menjadi Senjata Filsafat Kehidupan
- Asal-usul Kujang Banten
- Perbedaan Kujang Banten dan Kujang Sunda
- Makna Filosofis di Balik Bilah Kujang
- Ritual dan Kepercayaan di Sekitar Kujang
- Kujang dalam Kehidupan Modern
- Parang dan Bedog: Dari Alat Sawah Menjadi Senjata Perlawanan Rakyat
- Dari Sawah ke Medan Laga
- Bedog: Kawan Setia Para Jawara Desa
- Cerita Rakyat: Bedog dan Jawara yang Melawan Penjajah
- Ciri Khas Parang dan Bedog Banten
- Makna Simbolik Parang dan Bedog
- Congkrang & Arit: Senjata Tersembunyi yang Mematikan di Tangan Ahlinya
- Analisis Taktis: Efektivitas dalam Pertarungan Jarak Dekat
- Teknik Silat Banten yang Mengandalkan Congkrang dan Arit
- Bentuk Bilah: Bulan Sabit dan Baplang
- Bukan Sekadar Alat Bertani
- Makna Filosofis: Kecerdikan Mengalahkan Kekuasaan
- Tombak Banten: Senjata Para Prajurit Elit Kesultanan
- Peran Tombak dalam Formasi Perang Kesultanan Banten
- Jenis-jenis Tombak dalam Tradisi Banten
- Referensi dari Naskah Sejarah: Tombak dalam “Sajarah Banten”
- Pandangan Kurator: Tombak sebagai Simbol Kepemimpinan
- Tombak dalam Tradisi Modern
- Di Balik Bilah: Filosofi Pamor dan Desain Gagang Senjata Banten
- Pamor: Jejak Spiritual di Bilah Logam
- Desain Gagang: Keseimbangan Antara Genggaman dan Kekuatan
- Makna Keseimbangan: Fisik dan Batin
- Jejak Seni Pandai Besi Banten
- Senjata sebagai Cermin Budaya
- Golok Banten: Ikon Jawara dan Jati Diri Rakyat
- Lebih dari Sekadar Senjata Tajam
- Simbol Jawara: Antara Keberanian dan Etika
- Ragam Golok Khas Banten
- Golok dalam Seni Bela Diri Banten
- Golok dalam Kehidupan Modern
- Filosofi Golok: Ketegasan dan Kasih Sayang
- Jawara dan Spirit Perlawanan: Ketika Senjata Jadi Simbol Identitas
- Dari Laskar Rakyat ke Pahlawan Daerah
- Senjata sebagai Lambang Martabat
- Senjata dan Spirit Keteguhan
- Akulturasi Islam dan Kearifan Lokal
- Senjata sebagai Identitas Budaya
- Jejak dalam Catatan Sejarah
- Makna Bagi Generasi Sekarang
- Golok Ciomas: Pusaka Sakral Penjaga Kehormatan Tanah Banten
- Asal-usul dan Legenda Ki Cengkuk serta Ki Tundung
- Anatomi Golok Ciomas: Keseimbangan antara Kekuatan dan Keindahan
- Ciri Khas dan Tuah Golok Ciomas Asli
- Klasifikasi Golok Ciomas
- Proses Penyepuhan dan Gendam: Ritual Memberi “Isi” pada Bilah
- Golok Sulangkar: Bilah Kembar Penanda Status Sosial Para Bangsawan
- Kisah di Balik Sulangkar: Senjata Eksklusif bagi Kalangan Kesultanan
- Jejak Golok Sulangkar Milik Sultan Ageng Tirtayasa
- Perbedaan Golok Sulangkar dengan Golok Banten Lainnya
- Kisah Kolektor dan Warisan Keturunan Bangsawan
- Kujang Banten: Warisan Sunda yang Hidup di Tanah Kesultanan
- Dari Pajajaran ke Banten: Perjalanan Sebuah Senjata Suci
- Ciri Khas Kujang Banten
- Fungsi Simbolik: Senjata, Tanda Kebijaksanaan, dan Alat Ritual
- Kujang Sebagai Identitas Budaya Banten
- Makna Filosofis Kujang Banten
- Bedog dan Parang Pandeglang: Senjata Rakyat, Cermin Ketangguhan Petani Banten
- Asal-Usul Bedog: Dari Alat Dapur Jadi Senjata Jawara
- Parang Pandeglang: Senjata dari Tanah Petani dan Nelayan
- Ciri Visual dan Teknik Pembuatan
- Fungsi Sosial dan Filosofi Parang
- Bedog dan Parang: Dua Wajah yang Saling Melengkapi
- Badik dan Rencong Banten: Jejak Persilangan Budaya di Tanah Jawara
- Badik Banten: Dari Senjata Bugis Menjadi Simbol Keberanian Tanah Jawara
- Rencong Banten: Pengaruh Aceh di Tanah Kesultanan
- Jejak Arkeologis dan Catatan Tertulis
- Filosofi di Balik Dua Bilah
- Di Balik Bilah: Filosofi Pamor dan Desain Gagang Senjata Banten
- Pamor: Lukisan Doa di Atas Besi
- Gagang (Hulu): Simbol Kendali dan Kebijaksanaan
- Sarung (Warangka): Rasa, Penutup, dan Kesopanan
- Keseimbangan Kosmologis: Isi, Cipta, dan Rasa
- Pandangan Empu Ciomas
- Proses Penempaan Sakral: Kunjungan ke Pusat Pembuatan Senjata Tradisional Ciomas
- Menyusuri Bengkel Empu
- Wawancara dengan Empu Ciomas
- Proses Penempaan Langkah Demi Langkah
- Ritual dan Pantangan
- Galeri Foto dan Dokumentasi
- Makna di Balik Proses
- Panduan Kolektor: Cara Membedakan Pusaka Asli dan Palsu serta Etika Kepemilikan
- 1. Kenali Ciri Fisik Senjata Asli Banten
- 2. Ciri Non-Fisik: Energi dan Riwayat
- 3. Waspadai Pusaka Replika dan “Isi-Iisian”
- 4. Etika Kepemilikan Pusaka
- 5. Tips Membeli Secara Aman
- 6. Penegasan Nilai Budaya
- FAQ: Pertanyaan Umum tentang Senjata Tradisional Banten
- 1. Di mana saya bisa melihat koleksi senjata tradisional Banten yang asli?
- 2. Apakah Golok Ciomas masih dibuat hingga sekarang?
- 3. Apa senjata Banten yang paling sakti menurut cerita rakyat?
- 4. Bolehkah senjata pusaka Banten dimiliki oleh orang biasa?
- 5. Bagaimana cara belajar tentang senjata tradisional Banten lebih dalam?
- 6. Apakah senjata tradisional Banten diakui sebagai warisan budaya Indonesia?
- 7. Mengapa senjata tradisional Banten begitu terkenal dibanding daerah lain?
- Penutup: Warisan Pandai Besi Banten di Era Modern
Namun di balik ketangguhan itu, Banten juga menyimpan warisan budaya yang unik — yaitu senjata tradisional yang menjadi simbol kehormatan dan identitas masyarakatnya.
Senjata-senjata seperti Golok Ciomas, Golok Sulangkar, Kujang Banten, hingga Tombak Kesultanan bukan hanya alat bertarung. Bagi masyarakat Banten, senjata adalah pusaka yang memiliki jiwa, hasil perpaduan antara keterampilan teknis dan nilai spiritual.
Setiap bilah ditempa dengan doa, niat, dan pantangan tertentu. Prosesnya tak sekadar menempa besi, tapi juga membentuk karakter. Karena itu, senjata tradisional dianggap sebagai perpanjangan diri sang pemiliknya — mencerminkan keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab.
Dalam sejarahnya, Banten pernah menjadi pusat perdagangan dan kekuatan militer penting di Nusantara. Dari situlah muncul berbagai jenis senjata yang berfungsi tidak hanya untuk berperang, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan pelindung diri.
Kini, keberadaan senjata tradisional Banten menjadi bagian penting dari warisan budaya takbenda Indonesia. Ia merekam jejak sejarah, sekaligus menjadi bukti betapa kuatnya masyarakat Banten menjaga identitas dan nilai leluhurnya.
Artikel ini akan membawa kamu menelusuri tujuh senjata legendaris Banten. Kita akan membahas sejarahnya, filosofi di balik bilahnya, hingga proses pembuatannya yang masih bertahan sampai hari ini.
Mengapa Banten Dijuluki “Tanah Jawara”?
Julukan “Tanah Jawara” bukan sekadar kebanggaan lokal. Sebutan ini lahir dari sejarah panjang masyarakat Banten yang dikenal tangguh, pemberani, dan menjunjung tinggi kehormatan.
Istilah jawara sendiri berasal dari kata Jawa kuno “juwara” yang berarti orang unggul atau pahlawan. Dalam konteks Banten, jawara tak hanya berarti jago silat, tapi juga sosok yang mampu menjaga ketertiban, menegakkan kebenaran, dan melindungi rakyat kecil.
Sejak masa Kesultanan Banten pada abad ke-16, para jawara berperan penting dalam menjaga keamanan wilayah. Mereka bukan bagian dari pasukan resmi kerajaan, tetapi memiliki pengaruh besar di masyarakat. Banyak dari mereka juga menjadi murid para ulama dan tokoh agama. Itulah sebabnya, nilai keberanian di Banten selalu berpadu dengan moral dan spiritualitas.
Era Emas Kesultanan Banten: Poros Perdagangan dan Kekuatan Militer
Pada masa kejayaannya, Kesultanan Banten dikenal sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan di barat Pulau Jawa. Pelabuhan Banten menjadi tempat singgah para pedagang dari Arab, India, Cina, hingga Eropa.
Dalam konteks geopolitik Nusantara, Banten memiliki pasukan militer tangguh yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata lokal, termasuk tombak, parang, dan golok. Pasukan ini berperan besar dalam menjaga jalur perdagangan dan mempertahankan wilayah dari serangan asing.
Kekuatan militer itu tidak hanya bersumber dari jumlah prajurit, tapi juga dari penguasaan teknik bela diri lokal yang kelak menjadi akar dari tradisi pencak silat Banten.
Peran Jawara dan Pendekar dalam Struktur Sosial Masyarakat
Setelah masa kesultanan, peran para jawara dan pendekar tetap penting di tengah masyarakat. Mereka menjadi penjaga kampung, penengah sengketa, sekaligus simbol ketegasan moral.
Jawara bukan hanya jago bertarung. Dalam budaya Banten, mereka juga dikenal taat beragama dan hormat pada ulama.
Itulah sebabnya, istilah jawara sejati selalu dihubungkan dengan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kebijaksanaan batin.
Jejak Perlawanan Terhadap VOC
Ketika kekuasaan kolonial Belanda mulai masuk, banyak jawara Banten ikut dalam perlawanan rakyat. Mereka memanfaatkan senjata tradisional seperti golok dan bedog dalam taktik perang gerilya.
Perlawanan ini bukan hanya soal senjata, tapi juga bentuk perjuangan spiritual dan nasionalisme lokal.
Bagi masyarakat Banten, mengangkat senjata berarti menegakkan martabat dan mempertahankan tanah leluhur.
Catatan Sejarah: Tomé Pires dan Naskah Kuno
Catatan penjelajah Portugis Tomé Pires dalam Suma Oriental menyebut bahwa wilayah Banten telah dikenal sebagai daerah dengan prajurit pemberani dan pandai besi handal.
Beberapa naskah kuno juga menulis tentang tombak dan golok khas Banten yang digunakan oleh prajurit kerajaan dalam menghadapi serangan musuh.
Fakta-fakta ini memperkuat bahwa sejak dahulu, Banten bukan sekadar pusat perdagangan, tapi juga tempat lahirnya tradisi keprajuritan yang kuat.
Kini, semangat para jawara itu masih hidup dalam budaya masyarakat Banten. Ia tercermin dalam seni bela diri, ritual adat, hingga cara hidup yang menjunjung kehormatan.
Tak heran bila hingga sekarang, julukan “Tanah Jawara” tetap melekat erat di hati masyarakat Banten.
Golok Ciomas: Pusaka Sakral Penjaga Kehormatan Tanah Banten
Kalau bicara senjata tradisional Banten, nama Golok Ciomas pasti muncul di urutan pertama.
Bilahnya tajam, bentuknya gagah, dan pamornya berkilau — tapi yang membuatnya istimewa bukan sekadar bentuk fisiknya.
Golok Ciomas dikenal sebagai pusaka sakral yang menyimpan kekuatan spiritual.
Bagi masyarakat Banten, terutama di wilayah Ciomas, Kabupaten Serang, golok ini dianggap memiliki “isi” — semacam daya gaib atau tuah yang hanya dimiliki bilah tertentu.
Lebih dari itu, golok ini juga menjadi simbol kehormatan bagi para jawara.
Ia bukan alat kekerasan, tapi lambang tanggung jawab dan keberanian untuk menegakkan kebenaran.
Legenda Ki Cengkuk dan Ki Tundung: Asal-usul Golok Sakti “Si Denok”
Asal-usul Golok Ciomas tak lepas dari kisah dua empu legendaris: Ki Cengkuk dan Ki Tundung.
Keduanya dikenal sebagai pandai besi sakti yang hidup pada masa awal Kesultanan Banten.
Konon, mereka menempa sebilah golok dari logam langka yang ditemukan di gunung.
Saat ditempa, logam itu mengeluarkan suara seperti palu memukul genderang perang, sehingga bilahnya dijuluki “Si Denok” — artinya “yang berdentum”.
Legenda ini menjadi dasar keyakinan bahwa Golok Ciomas bukan sekadar senjata, tapi juga memiliki roh penjaga yang hanya menghuni bilah buatan empu tertentu.
Anatomi Golok Ciomas: Gagang, Simpay, Bilah, dan Warangka
Secara teknis, Golok Ciomas memiliki struktur yang khas dan proporsional.
Bagian bilahnya cenderung tebal di pangkal dan meruncing di ujung, mencerminkan keseimbangan antara daya tebas dan kelincahan.
Gagang (hulu) biasanya dibuat dari kayu keras seperti kayu nangka atau sonokeling.
Sementara simpay (sarung) terbuat dari kayu yang dilapisi anyaman atau ukiran sederhana.
Beberapa bilah memiliki pamor alami — pola gelombang logam yang muncul karena campuran besi dan baja saat ditempa.
Pamor ini sering dianggap punya makna spiritual, seperti lambang kesetiaan atau keteguhan hati.
Ciri Khas dan Tuah Golok Ciomas Asli
Golok Ciomas asli bisa dibedakan dari bentuk dan pamornya.
Biasanya memiliki bentuk melengkung halus, ujung runcing, dan berat yang seimbang.
Empu Ciomas juga dikenal menggunakan bahan besi pilihan yang sudah ditempa berulang kali.
Dalam tradisi lokal, bilah golok dianggap memiliki “tuah” tertentu.
Ada yang dipercaya memberi perlindungan, ada pula yang membawa wibawa bagi pemiliknya.
Namun, masyarakat Banten menekankan bahwa tuah sejati datang dari niat dan moral pemiliknya, bukan dari benda itu sendiri.
Jenis-Jenis Golok Ciomas
Para kolektor dan ahli budaya mengenal beberapa varian Golok Ciomas, di antaranya:
- Salam Nunggal – bilah tunggal tanpa sambungan, simbol keutuhan jiwa.
- Kembang Kacang – punya lekukan khas di pangkal bilah, melambangkan kesuburan dan rezeki.
- Mamancungan – ujungnya runcing dan tajam, sering digunakan dalam pertarungan jarak dekat.
Setiap jenis punya filosofi sendiri, mencerminkan karakter dan tujuan pemiliknya.
Ritual Penyepuhan dan Gendam: Menghidupkan Bilah
Proses pembuatan Golok Ciomas tidak hanya teknis, tapi juga spiritual.
Sebelum ditempa, empu biasanya menjalani puasa, doa, dan ritual penyepuhan.
Penyepuhan bukan hanya untuk mengeraskan besi, tapi juga mengisi energi spiritual ke dalam bilah.
Ada pula ritual gendam, yaitu pembacaan doa tertentu agar golok menjadi “berisi” dan menyatu dengan pemiliknya.
Ritual-ritual ini dijaga ketat dan tidak semua empu boleh melakukannya.
Hanya mereka yang dianggap sudah matang secara ilmu dan batin yang boleh menempa Golok Ciomas sejati.
Kini, Golok Ciomas tak hanya dianggap pusaka, tapi juga ikon budaya Banten.
Banyak kolektor, peneliti, dan wisatawan datang ke Ciomas untuk melihat langsung proses penempaan tradisionalnya.
Warisan ini menjadi bukti bahwa spirit para jawara masih hidup di tengah masyarakat modern.
Golok Sulangkar: Bilah Kembar Simbol Kekuatan dan Kehormatan Bangsawan Banten
Berbeda dengan Golok Ciomas yang identik dengan para jawara rakyat, Golok Sulangkar dulu menjadi lambang status sosial para pejabat dan bangsawan Banten.
Senjata ini dikenal karena bentuknya yang kembar, elegan, dan penuh makna simbolik.
Nama “Sulangkar” berasal dari kata sulang (berpasangan) dan akar (kesatuan).
Artinya, dua bilah yang berbeda tapi saling melengkapi — menggambarkan keselarasan antara kekuatan dan kebijaksanaan.
Asal-usul Golok Sulangkar: Dari Istana Kesultanan hingga Warisan Jawara
Menurut catatan lisan masyarakat Serang dan Pandeglang, Golok Sulangkar pertama kali digunakan di lingkungan Kesultanan Banten pada abad ke-17.
Golok ini biasanya menjadi pelengkap pakaian kebesaran para bangsawan dan prajurit istana.
Namun, seiring waktu, senjata ini juga diadopsi oleh para jawara di pedesaan sebagai simbol kehormatan dan kedisiplinan.
Bagi mereka, memiliki sepasang Golok Sulangkar berarti sudah mencapai tingkat spiritual dan keterampilan tinggi.
Desain Bilah Kembar yang Penuh Filosofi
Golok Sulangkar memiliki dua bilah identik yang disimpan dalam satu wadah atau dibawa di dua sisi pinggang.
Setiap bilah memiliki panjang sekitar 30–40 cm, dengan ujung sedikit melengkung.
Satu bilah mewakili “tenaga lahir” (kekuatan fisik), sedangkan bilah lainnya melambangkan “tenaga batin” (kearifan dan pengendalian diri).
Konsep ini menggambarkan filosofi dualitas dan keseimbangan, mirip dengan konsep Yin dan Yang di budaya Timur.
Material dan Detail Ukiran Golok Sulangkar
Bahan utama Golok Sulangkar biasanya adalah baja tempa berpadu dengan pamor alami.
Gagangnya sering dihiasi ukiran flora atau motif geometris yang menunjukkan derajat pemiliknya.
Pada masa Kesultanan, beberapa bilah bahkan diberi lapisan perak atau kuningan di bagian gagang sebagai penanda status sosial tinggi.
Sarungnya (simpay) dibuat dari kayu pilihan dengan ukiran halus dan anyaman rotan pengikat.
Keseluruhan tampilannya memancarkan kesan mewah namun berwibawa, sesuai fungsinya sebagai senjata sekaligus simbol kehormatan.
Fungsi dan Makna Sosial Golok Sulangkar
Golok Sulangkar tidak hanya berfungsi sebagai alat bela diri.
Ia juga menjadi penanda identitas sosial dan spiritual seseorang.
Para bangsawan membawa Golok Sulangkar saat upacara adat, pertemuan resmi, atau penyambutan tamu kehormatan.
Sementara bagi para jawara, golok ini menjadi simbol penguasaan diri dan keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan.
Ritual dan Etika Kepemilikan Golok Sulangkar
Dalam budaya Banten, memiliki Golok Sulangkar tidak bisa sembarangan.
Seseorang harus “layak” secara moral dan spiritual sebelum menyandangnya.
Biasanya dilakukan ritual penyerahan atau penobatan, di mana seorang guru atau sesepuh memberikan sepasang bilah kepada muridnya.
Ritual ini menandakan bahwa si murid sudah siap mengemban tanggung jawab sebagai penjaga kehormatan.
Golok Sulangkar bukan sekadar benda, tapi cermin karakter pemiliknya — apakah ia mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebaikan.
Golok Sulangkar di Masa Kini
Kini, Golok Sulangkar lebih sering dijumpai sebagai koleksi budaya dan benda pusaka.
Banyak museum daerah dan kolektor pribadi di Banten yang menyimpannya sebagai warisan leluhur.
Namun, nilai filosofisnya tetap relevan.
Dalam dunia modern, Sulangkar mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang fisik, tapi tentang kemampuan menahan diri dan menegakkan martabat.
Kujang Banten: Dari Alat Pertanian Menjadi Senjata Filsafat Kehidupan
Kebanyakan orang mengenal Kujang sebagai senjata khas Sunda dari tanah Priangan.
Namun, di Banten, Kujang punya versi dan makna yang sedikit berbeda.
Bagi masyarakat Banten, Kujang bukan sekadar senjata tajam, tapi juga lambang kesuburan, keseimbangan, dan keteguhan hidup.
Bentuknya yang unik dan penuh simbol menjadikannya senjata yang “berbicara” tentang karakter manusia dan alam.
Asal-usul Kujang Banten
Secara historis, Kujang diperkirakan berasal dari abad ke-8 pada masa Kerajaan Pajajaran.
Saat itu, fungsinya masih sebagai alat pertanian — digunakan untuk menebas rumput atau membuka lahan.
Namun, setelah wilayah Banten berkembang menjadi kerajaan Islam yang mandiri, bentuk Kujang pun bertransformasi menjadi simbol spiritual dan senjata kehormatan.
Kujang versi Banten dikenal lebih ramping, lebih tajam, dan punya lekukan khas yang disebut “eluk” di bagian bilahnya.
Perbedaan Kujang Banten dan Kujang Sunda
Walau sama-sama disebut Kujang, bentuk dan filosofi keduanya agak berbeda.
Kujang Sunda cenderung memiliki bentuk melengkung lebar dengan ornamen rumit.
Sementara Kujang Banten lebih minimalis dan fungsional, menandakan karakter masyarakat pesisir yang keras dan langsung.
Kujang Banten juga biasanya tidak terlalu banyak ukiran simbolik, melainkan menonjolkan sisi kekuatan dan kegunaannya.
Namun maknanya tetap dalam — mencerminkan keseimbangan antara tenaga, niat, dan ketulusan.
Makna Filosofis di Balik Bilah Kujang
Bentuk Kujang dianggap mengandung lima lekukan utama, yang masing-masing mewakili nilai kehidupan manusia:
- Niat – dasar dari setiap tindakan.
- Rasa – pengendali emosi dan kebijaksanaan.
- Karsa – semangat juang dan keteguhan hati.
- Laku – perbuatan nyata yang membawa hasil.
- Raga – wadah dari seluruh energi kehidupan.
Bagi masyarakat Banten, membawa Kujang berarti membawa tanggung jawab moral.
Ia mengingatkan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran.
Ritual dan Kepercayaan di Sekitar Kujang
Seperti Golok Ciomas, Kujang juga sering dianggap memiliki “isi” atau daya spiritual.
Sebelum digunakan, biasanya dilakukan ritual penyucian dan pembacaan doa.
Ada kepercayaan bahwa Kujang akan “hidup” bila dimiliki oleh orang yang benar-benar jujur dan berani.
Jika dipakai oleh orang yang tamak atau sombong, bilahnya bisa menjadi tumpul atau bahkan “berat dipegang”.
Ritual ini bukan takhayul kosong, tapi bentuk pengendalian moral, agar pemiliknya selalu ingat pada nilai-nilai luhur nenek moyang.
Kujang dalam Kehidupan Modern
Kini, Kujang Banten tidak lagi digunakan untuk bertarung.
Ia lebih sering tampil sebagai hiasan simbolik, logo lembaga, atau souvenir budaya yang menandakan identitas daerah.
Namun maknanya tetap hidup — bahwa kekuatan sejati bukan pada bilahnya, tapi pada niat dan hati pemiliknya.
Nilai ini membuat Kujang Banten tetap relevan sebagai filsafat hidup orang Banten yang tegas, berani, tapi selalu menjaga keseimbangan.
Parang dan Bedog: Dari Alat Sawah Menjadi Senjata Perlawanan Rakyat
Kalau Golok Ciomas identik dengan para jawara, maka Parang dan Bedog adalah senjata milik rakyat biasa.
Dua alat sederhana ini lahir dari keseharian masyarakat Banten yang akrab dengan alam, bekerja di ladang, dan hidup mandiri.
Awalnya, Parang dan Bedog hanya digunakan untuk bercocok tanam, menebas rumput, atau membuka hutan.
Namun, saat masa penjajahan tiba, alat-alat ini berubah fungsi menjadi senjata perlawanan rakyat.
Dari Sawah ke Medan Laga
Dalam banyak kisah lisan di pedesaan Banten, para petani sering digambarkan berubah menjadi jawara ketika tanah mereka dirampas.
Parang yang biasanya digunakan untuk menebang bambu, kini diayunkan untuk melawan penjajah atau tuan tanah yang sewenang-wenang.
Keberanian rakyat Banten bukan hanya karena dendam, tapi karena rasa tanggung jawab terhadap tanah kelahiran.
Itulah mengapa Parang dan Bedog dianggap sebagai senjata rakyat — simbol perlawanan tanpa pamrih.
Bedog: Kawan Setia Para Jawara Desa
Istilah Bedog di Banten mengacu pada golok besar atau parang panjang.
Desainnya sederhana tapi kuat. Gagangnya biasanya terbuat dari kayu nangka atau jati, sedangkan bilahnya dari besi tempa tradisional.
Setiap Bedog dibuat sesuai kebutuhan pemiliknya — ada yang besar untuk memotong kayu, ada pula yang kecil untuk keperluan harian.
Tapi di tangan orang yang terlatih, Bedog bisa menjadi senjata yang sangat mematikan.
Cerita Rakyat: Bedog dan Jawara yang Melawan Penjajah
Salah satu cerita terkenal berasal dari daerah Pandeglang dan Lebak.
Konon, seorang jawara bernama Ki Suraksa menggunakan Bedog peninggalan ayahnya untuk melawan patroli Belanda di hutan.
Dengan keberanian luar biasa, ia menebas rantai kuda penjajah — simbol kebebasan bagi rakyatnya.
Walau kisah ini bercampur antara sejarah dan legenda, maknanya jelas:
Bedog bukan sekadar besi tajam, tapi simbol keberanian rakyat kecil yang tak pernah menyerah.
Ciri Khas Parang dan Bedog Banten
Bilah Parang Banten cenderung tebal dan agak melengkung di ujungnya.
Bentuk ini membuatnya efektif baik untuk menebas maupun menusuk.
Sementara Bedog biasanya punya punggung bilah datar dan ujung runcing — ideal untuk pekerjaan berat sekaligus pertahanan diri.
Keduanya sering diselipkan di pinggang menggunakan sarung sederhana dari kulit atau kayu.
Bentuknya mungkin tak seindah pusaka bangsawan, tapi kekuatannya nyata — hasil kerja tangan rakyat yang tulus dan keras.
Makna Simbolik Parang dan Bedog
Bagi masyarakat Banten, Parang dan Bedog mewakili etos kerja keras, kejujuran, dan kemandirian.
Siapa pun yang membawa Bedog dianggap siap bekerja dan siap membela diri.
Dalam falsafah lokal, “Bilah tanpa niat adalah besi mati, niat tanpa bilah adalah keberanian tanpa bentuk.”
Kalimat ini mengingatkan bahwa kekuatan sejati lahir dari keseimbangan antara kerja nyata dan tekad hati.
Kini, Parang dan Bedog tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Banten.
Sebagian dijadikan koleksi budaya, sebagian lain masih digunakan petani di pedesaan.
Namun nilainya tak pernah berkurang: mewakili semangat rakyat Banten yang teguh, pekerja keras, dan pantang tunduk.
Congkrang & Arit: Senjata Tersembunyi yang Mematikan di Tangan Ahlinya
Sekilas, Congkrang dan Arit terlihat seperti alat pertanian biasa.
Tapi di tangan masyarakat Banten, dua benda ini bisa berubah menjadi senjata yang cepat, senyap, dan mematikan.
Keduanya sering disebut sebagai “senjata rakyat lapisan bawah” — sederhana, tapi sarat filosofi tentang kecerdikan dan ketahanan hidup.
Dalam sejarahnya, Congkrang dan Arit memainkan peran penting dalam perlawanan petani terhadap penjajah maupun penguasa lokal.
Analisis Taktis: Efektivitas dalam Pertarungan Jarak Dekat
Dibandingkan senjata besar seperti tombak atau golok, Congkrang dan Arit jauh lebih kecil dan ringan.
Namun justru di situlah keunggulannya: mudah disembunyikan, cepat digunakan, dan sulit ditebak arah serangannya.
Bentuknya melengkung seperti bulan sabit, memungkinkan pengguna melakukan gerakan mengait, mengunci, atau menebas dengan kecepatan tinggi.
Dalam pertarungan jarak dekat, satu ayunan tajam di pergelangan tangan bisa langsung melumpuhkan lawan.
Teknik Silat Banten yang Mengandalkan Congkrang dan Arit
Dalam tradisi pencak silat Banten, terutama aliran Debus dan Bandrong, Arit dan Congkrang punya tempat tersendiri.
Gerakannya cenderung mengalir dan mematuk cepat, mirip serangan hewan liar.
Para jawara mempelajari teknik seperti:
- Kuncian sabit (menangkap senjata lawan dengan lengkungan bilah)
- Koyakan cepat (serangan geser yang memotong tanpa tenaga besar)
- Sabet balik (ayunan balik dengan momentum putaran tubuh).
Latihan ini bukan hanya untuk bertarung, tapi juga untuk melatih refleks, fokus, dan kendali diri.
Bentuk Bilah: Bulan Sabit dan Baplang
Ada dua bentuk utama yang dikenal masyarakat Banten:
- Arit Bulan Sabit, dengan lengkungan sempurna, cocok untuk serangan melingkar.
- Arit Baplang, dengan bilah lebar dan tajam pada satu sisi — lebih mirip pisau tebas daripada sabit.
Bahan pembuatnya biasanya besi tempa lokal, disepuh agar tahan karat dan mudah diasah.
Sementara gagangnya sering dibuat dari kayu nangka, bambu, atau tulang kerbau.
Bukan Sekadar Alat Bertani
Pada masa kolonial, petani Banten dilarang membawa senjata tajam.
Tapi karena Arit dianggap alat kerja, mereka bisa tetap membawanya tanpa dicurigai.
Dari sinilah muncul banyak kisah pemberontakan petani yang menggunakan Arit dan Congkrang untuk melawan penjajah.
Senjata sederhana ini menjadi simbol perlawanan tersembunyi, perlawanan rakyat kecil yang tak mau ditindas.
Makna Filosofis: Kecerdikan Mengalahkan Kekuasaan
Bagi orang Banten, Congkrang dan Arit mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya soal tenaga, tapi juga strategi.
Seperti sabit yang melengkung, hidup pun butuh keluwesan untuk menghadapi tantangan.
Filosofi ini sejalan dengan nilai “silih asah, silih asih, silih asuh” — saling mengasah kemampuan, menyayangi, dan menjaga satu sama lain.
Jadi, Congkrang bukan cuma alat atau senjata, tapi juga cermin kebijaksanaan rakyat kecil yang cerdas dan tangguh.
Kini, Arit dan Congkrang masih bisa ditemukan di rumah-rumah petani Banten.
Tapi nilai simboliknya tetap hidup — ketajaman bukan di bilahnya, melainkan di pikiran dan hati penggunanya.
Tombak Banten: Senjata Para Prajurit Elit Kesultanan
Sebelum dikenal sebagai provinsi modern, Banten pernah menjadi salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Nusantara.
Di masa Kesultanan Banten (abad ke-16 hingga ke-18), kekuatan militernya ditakuti banyak pihak — dari Portugis hingga VOC Belanda.
Di antara berbagai jenis senjata yang digunakan, tombak menempati posisi istimewa.
Ia bukan hanya senjata perang, tapi juga simbol keberanian, kepemimpinan, dan kehormatan prajurit elit Kesultanan.
Peran Tombak dalam Formasi Perang Kesultanan Banten
Pasukan Kesultanan Banten dikenal disiplin dan terlatih.
Dalam catatan sejarah, mereka menggunakan formasi berlapis, di mana barisan depan membawa tombak panjang (lancing), sementara barisan belakang menggunakan pedang atau busur.
Tombak menjadi senjata utama untuk menahan serangan kavaleri dan infanteri lawan.
Ujungnya dibuat dari besi tempa yang disepuh hingga mampu menembus perisai bambu dan baju zirah logam tipis.
Tombak juga digunakan dalam upacara kerajaan, sebagai lambang kesiapsiagaan dan kewibawaan pasukan Kesultanan.
Jenis-jenis Tombak dalam Tradisi Banten
Menurut penelusuran naskah-naskah kuno dan koleksi museum daerah, dikenal beberapa jenis tombak khas Banten:
- Tombak Lading – bilahnya lurus dan panjang, cocok untuk tusukan langsung.
- Tombak Naga Siluman – bilahnya berliku seperti lidah api, sering dianggap punya kekuatan spiritual.
- Tombak Balang – lebih pendek, digunakan untuk lemparan jarak menengah.
- Tombak Kiai Gede – tombak pusaka kerajaan, disimpan untuk upacara atau simbol kekuasaan.
Setiap jenis tombak punya pamor dan ukiran berbeda, menggambarkan derajat dan fungsi pemiliknya.
Referensi dari Naskah Sejarah: Tombak dalam “Sajarah Banten”
Dalam naskah Sajarah Banten disebutkan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa memiliki tombak sakral bernama Kiai Pamungkas.
Konon, tombak ini selalu dibawa dalam perang dan dianggap membawa keberanian bagi pasukannya.
Catatan lain dari pengelana Portugis, Tomé Pires, juga menyebut bahwa “prajurit Banten bersenjata tombak panjang dan tameng rotan, bertempur dengan semangat tak kenal takut.”
Ini menunjukkan bahwa tombak adalah jantung kekuatan militer Banten.
Pandangan Kurator: Tombak sebagai Simbol Kepemimpinan
Kurator Museum Negeri Banten, dalam wawancaranya dengan sejumlah media, menjelaskan:
“Tombak bukan sekadar alat perang. Dalam tradisi Banten, ia adalah simbol kepemimpinan — karena hanya pemimpin sejati yang bisa menjaga jarak antara kekuasaan dan keangkuhan.”
Makna ini sangat dalam.
Tombak memang senjata jarak jauh, tapi filosofi di baliknya justru menekankan kendali diri, kesabaran, dan kehormatan.
Tombak dalam Tradisi Modern
Kini, tombak-tombak peninggalan Kesultanan masih disimpan di Museum Negeri Banten, Museum Nasional Indonesia, dan koleksi keluarga keturunan bangsawan lokal.
Beberapa masih digunakan dalam ritual kebudayaan dan atraksi silat tradisional.
Keberadaannya menjadi pengingat bahwa Banten pernah berdiri gagah sebagai pusat kekuatan dan kebudayaan besar di Nusantara.
Di Balik Bilah: Filosofi Pamor dan Desain Gagang Senjata Banten
Setiap senjata tradisional Banten bukan sekadar alat tempur.
Ia juga karya seni yang memadukan teknik pandai besi, filosofi hidup, dan spiritualitas lokal.
Bagi masyarakat Banten tempo dulu, bilah dan gagang senjata mencerminkan jati diri dan kehormatan pemiliknya.
Pamor: Jejak Spiritual di Bilah Logam
Pamor adalah corak atau guratan alami pada bilah senjata, terutama pada golok dan keris Banten.
Corak ini terbentuk dari paduan logam berbeda seperti besi, nikel, dan baja yang ditempa berulang-ulang.
Namun, pamor bukan sekadar hiasan.
Setiap pola dipercaya punya makna simbolik dan energi tertentu.
Beberapa jenis pamor yang dikenal di Banten antara lain:
- Pamor Udan Mas – melambangkan rezeki yang mengalir deras seperti hujan emas.
- Pamor Wos Wutah – menggambarkan keberanian yang tumpah-ruah, cocok untuk pendekar.
- Pamor Ngulit Semangka – dipercaya memberi perlindungan dari bahaya dan tipu daya musuh.
Pandai besi Banten sering melakukan tirakat (puasa dan doa khusus) sebelum menempah bilah.
Tujuannya: agar senjata itu “berjiwa” dan menjadi pelindung, bukan sekadar benda tajam.
Desain Gagang: Keseimbangan Antara Genggaman dan Kekuatan
Gagang senjata Banten, terutama pada golok dan tombak, dibuat dengan desain ergonomis dan penuh simbol.
Biasanya menggunakan bahan kayu jati, tanduk kerbau, atau akar bahar.
Bentuknya tak asal.
Ada yang melengkung lembut sebagai simbol keluwesan hati, ada juga yang tegak kaku melambangkan keteguhan tekad.
Pada beberapa senjata pusaka, gagang dihiasi ukiran harimau, naga, atau burung garuda.
Setiap motif membawa pesan filosofis:
- Harimau = keberanian.
- Naga = kekuatan spiritual.
- Garuda = kemerdekaan dan wibawa.
Makna Keseimbangan: Fisik dan Batin
Dalam budaya Banten, seorang pendekar sejati tak diukur dari seberapa tajam senjatanya, tapi seberapa tajam budi dan nuraninya.
Pamor di bilah melambangkan keteguhan batin, sementara gagang yang kokoh melambangkan kendali diri.
Keduanya harus seimbang — karena kekuatan tanpa pengendalian hanyalah kehancuran.
Filosofi ini juga sejalan dengan nilai-nilai tasawuf Islam yang berkembang di Kesultanan Banten, di mana setiap tindakan harus dilandasi niat suci dan kesadaran spiritual.
Jejak Seni Pandai Besi Banten
Hingga kini, seni tempa logam khas Banten masih bisa ditemukan di beberapa daerah seperti Pandeglang, Cibaliung, dan Lebak.
Para empu atau pandai besi di sana dikenal masih menggunakan cara tradisional:
menggabungkan logam panas, menempanya dengan irama pukulan, sambil melafalkan doa-doa tertentu.
Setiap empu punya “tangan dingin” dan gaya tempa yang khas.
Konon, bilah dari Empu Lebak terkenal tajam, sedangkan bilah dari Cibaliung dikenal kuat dan awet.
Senjata sebagai Cermin Budaya
Melihat bilah dan gagang senjata Banten berarti melihat refleksi kebudayaan yang menyatukan seni, spiritualitas, dan sejarah.
Bukan hanya benda pusaka, tapi identitas kolektif masyarakat Banten — yang menjunjung kehormatan, keberanian, dan keseimbangan hidup.
Golok Banten: Ikon Jawara dan Jati Diri Rakyat
Kalau tombak adalah simbol para prajurit kerajaan,
maka golok adalah senjata rakyat.
Ia hidup di tengah masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi —
bukan cuma alat bertahan diri, tapi juga lambang harga diri dan kehormatan orang Banten.
Lebih dari Sekadar Senjata Tajam
Golok Banten bukan sembarang pisau besar.
Setiap lekuk bilah, setiap ukiran di gagang, punya arti mendalam.
Bentuknya sederhana tapi tangguh — melengkung sedikit di ujung, berat di tengah,
dan punya keseimbangan sempurna antara daya potong dan kendali tangan.
Di masa lalu, golok digunakan untuk berburu, bertani, sekaligus bertarung.
Ia adalah bagian dari keseharian: dari ladang, hutan, sampai gelanggang silat.
Simbol Jawara: Antara Keberanian dan Etika
Dalam budaya Banten, “jawara” bukan sekadar petarung tangguh.
Seorang jawara sejati harus adil, berani, dan punya tanggung jawab moral.
Mereka menjaga kampung, melindungi rakyat kecil, dan menjunjung martabat daerahnya.
Golok menjadi simbolnya —
tajam di luar, tapi berjiwa lembut di dalam.
Orang tua dulu bilang:
“Golok bukan buat mainan, tapi buat menjaga nama baik.”
Karena itu, golok selalu disimpan dengan hormat, sering dibungkus kain putih atau disimpan di tempat khusus.
Ia dianggap punya “isi” — bukan mistis, tapi energi dari niat baik pemiliknya.
Ragam Golok Khas Banten
Beberapa jenis golok tradisional Banten masih dikenal sampai sekarang:
- Golok Ciomas – dari Pandeglang, paling terkenal karena ketajamannya dan dipercaya punya aura magis.
- Golok Pamungkas – bilahnya lebar, gagangnya melengkung ke bawah, simbol dari keteguhan hati.
- Golok Badik Banten – pengaruh dari Bugis-Makassar, bilah lebih ramping dan menusuk dalam.
- Golok Betok – golok harian petani, ringan dan praktis untuk kerja di ladang.
Masing-masing golok punya ciri khas dan cerita rakyatnya sendiri.
Banyak juga yang dikaitkan dengan tokoh legendaris seperti Ki Wasyid, Jawara Pandeglang, dan Ki Dukun Binuangeun.
Golok dalam Seni Bela Diri Banten
Dalam seni bela diri tradisional seperti Pencak Silat Cimande, TTKDH, dan Bandrong,
golok digunakan bukan untuk menyerang, tapi melatih pengendalian diri dan ketepatan gerak.
Gerakannya cepat, tegas, tapi tetap terukur.
Seorang pendekar sejati justru belajar bagaimana tidak menggunakan golok,
karena kemenangan sejati ada pada penguasaan diri, bukan lawan.
Golok dalam Kehidupan Modern
Sekarang, golok sudah menjadi ikon budaya dan cenderamata khas Banten.
Banyak pengrajin di daerah Ciomas, Cihara, dan Lebak masih membuatnya secara tradisional.
Proses tempa bisa butuh berhari-hari — dari memilih logam, menempa, sampai memoles pamor bilahnya.
Bahkan, di beberapa festival budaya dan acara resmi, golok dijadikan simbol persaudaraan.
Misalnya dalam tradisi “Seblang Golok”, di mana dua jawara saling bersalaman sambil mengadu bilah tanpa niat menyakiti.
Filosofi Golok: Ketegasan dan Kasih Sayang
Golok Banten mengajarkan keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang.
Tajamnya bilah melambangkan keberanian menegakkan kebenaran,
sementara hiasan di gagang melambangkan keindahan budi.
Inilah alasan kenapa golok bukan sekadar alat, tapi manifestasi karakter masyarakat Banten: keras tapi beretika, berani tapi berjiwa santun.
Jawara dan Spirit Perlawanan: Ketika Senjata Jadi Simbol Identitas
Banten dikenal sebagai tanah para jawara.
Istilah jawara bukan hanya menunjuk pada petarung atau ahli silat,
tapi juga figur yang dihormati karena keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab sosialnya.
Mereka adalah penjaga kampung, pelindung rakyat kecil,
dan simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas.
Dari Laskar Rakyat ke Pahlawan Daerah
Sejak abad ke-17, saat Kesultanan Banten mulai diganggu oleh ekspansi VOC,
para jawara ikut berjuang mempertahankan tanahnya.
Mereka bukan tentara resmi, tapi prajurit rakyat yang mengandalkan keahlian silat dan senjata buatan sendiri.
Nama-nama seperti Ki Wasyid, Pangeran Aria, dan Haji Tubagus Ismail
menjadi legenda dalam berbagai perlawanan rakyat —
terutama dalam Pemberontakan Petani Banten tahun 1888,
yang tercatat dalam arsip kolonial Belanda sebagai salah satu gerakan rakyat paling kuat di Jawa.
Senjata sebagai Lambang Martabat
Setiap jawara punya golok atau bedog yang tidak sembarang dibuat.
Golok itu bukan cuma alat bertarung, tapi juga cermin harga diri dan kehormatan.
Bila seorang jawara gugur, goloknya diserahkan kepada keluarga,
disimpan dengan penuh hormat — karena diyakini “roh perjuangannya” melekat pada bilah itu.
Dalam beberapa keluarga di Pandeglang dan Lebak,
tradisi menyimpan golok warisan masih dilakukan sampai sekarang.
Mereka percaya, selama golok itu dirawat, semangat leluhur tetap hidup.
Senjata dan Spirit Keteguhan
Filosofi senjata tradisional Banten tak pernah jauh dari nilai spiritual.
Sebelum membuat atau menggunakan golok, empu dan pemiliknya wajib melakukan ritual tertentu —
mulai dari puasa mutih, dzikir malam, sampai penyepuhan dengan doa khusus.
Bukan untuk mistik semata, tapi untuk memastikan bahwa niat pemiliknya tidak salah arah.
Golok harus digunakan untuk membela yang benar, bukan menindas yang lemah.
Akulturasi Islam dan Kearifan Lokal
Uniknya, budaya jawara Banten tidak terpisah dari pengaruh Islam.
Ajaran ulama besar seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Nawawi al-Bantani
mendorong para pendekar untuk berjuang “fi sabilillah” —
menegakkan keadilan dan menolak kedzaliman dengan ilmu dan keberanian.
Dari sinilah lahir falsafah yang sering diucapkan orang tua Banten:
“Jawara sejati itu berilmu, berani, dan berakhlak.”
Makanya, banyak perguruan silat tradisional di Banten yang menjadikan doa, wirid, dan etika sebagai bagian utama dari latihan.
Senjata sebagai Identitas Budaya
Seiring waktu, golok, tombak, dan kujang Banten
tidak hanya menjadi alat bertarung, tapi identitas budaya yang membedakan masyarakat Banten dari daerah lain.
Kalau di Jawa Tengah orang punya keris,
maka di Banten, golok adalah simbol maskulinitas, keberanian, dan tanggung jawab sosial.
Bahkan sampai sekarang, dalam acara adat seperti seren taun, debus, atau pengantin jawara,
golok tetap hadir sebagai lambang kekuatan sekaligus doa keselamatan.
Jejak dalam Catatan Sejarah
Penulis Portugis Tomé Pires dalam catatan Suma Oriental (abad ke-16)
menyebut bahwa penduduk Banten “terlatih dalam perang dan sangat tangguh dalam pertarungan jarak dekat.”
Catatan lain dari VOC juga menulis tentang laskar Banten
yang “berani menghadapi senjata api dengan pedang dan tombak tanpa gentar.”
Ini menunjukkan bahwa senjata tradisional Banten
tidak hanya berfungsi praktis, tapi juga menjadi manifestasi ideologi perlawanan.
Makna Bagi Generasi Sekarang
Bagi generasi muda, kisah tentang senjata dan jawara bukan cuma nostalgia.
Ia adalah cermin karakter masyarakat Banten yang pantang menyerah, mandiri, dan berani menegakkan kebenaran.
Karena itu, mengenali senjata tradisional berarti juga memahami jiwa perlawanan dan nilai kemanusiaan yang diwariskan dari masa ke masa.
Golok Ciomas: Pusaka Sakral Penjaga Kehormatan Tanah Banten
Golok Ciomas adalah senjata yang paling identik dengan Banten.
Bukan hanya karena bentuk dan ketajamannya yang luar biasa,
tapi juga karena kisah sakral di balik pembuatannya yang diyakini penuh nilai spiritual.
Bagi masyarakat Banten, terutama di daerah Ciomas, Pandeglang,
golok ini bukan sekadar senjata tajam, melainkan pusaka hidup —
simbol kehormatan, keberanian, dan ketaatan pada nilai-nilai leluhur.
Asal-usul dan Legenda Ki Cengkuk serta Ki Tundung
Asal mula Golok Ciomas tak lepas dari kisah dua empu legendaris: Ki Cengkuk dan Ki Tundung.
Keduanya disebut sebagai pandai besi yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menempa besi hingga menjadi senjata bertuah.
Konon, mereka membuat golok menggunakan palu godam besar yang dijuluki “Si Denok.”
Palu ini dipercaya bisa mengeluarkan bunyi khas yang dianggap sebagai tanda restu alam.
Setiap kali palu itu menghantam besi panas, doa dan niat baik disertakan,
hingga terbentuklah bilah yang bukan hanya tajam secara fisik, tetapi juga “berisi.”
Legenda ini diwariskan turun-temurun dan dipercaya menjadi sebab mengapa golok Ciomas selalu diperlakukan dengan hormat.
Tidak sembarang orang boleh memilikinya, apalagi menempa ulang tanpa izin atau niat yang benar.
Anatomi Golok Ciomas: Keseimbangan antara Kekuatan dan Keindahan
Secara teknis, Golok Ciomas memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari golok daerah lain.
Bagian gagang (hulu) umumnya terbuat dari tanduk kerbau atau kayu pilihan, sering kali diukir halus dengan motif flora.
Bilahnya sedikit melengkung dengan bagian punggung yang tebal dan ujung menipis untuk efisiensi tebasan.
Di bagian tengah bilah, sering terlihat pola pamor — guratan alami dari hasil tempa besi dan baja berlapis.
Pamor ini bukan sekadar hiasan, melainkan cerminan keseimbangan unsur tanah, api, air, dan udara yang diyakini memberi kekuatan pada senjata.
Sarung atau warangka biasanya dibuat dari kayu nangka atau sonokeling,
dengan bentuk sederhana namun kuat, menandakan karakter masyarakat Banten yang tegas tapi tidak berlebihan.
Ciri Khas dan Tuah Golok Ciomas Asli
Golok Ciomas asli mudah dikenali dari bilahnya yang berat namun seimbang, serta bunyi khas ketika diayunkan.
Menurut para empu, suara itu berasal dari harmoni antara lapisan logam dan sepuhannya yang sempurna.
Selain keunggulan teknis, masyarakat juga meyakini bahwa golok Ciomas memiliki tuah —
bukan dalam arti mistik berlebihan, tetapi sebagai lambang perlindungan dan keberanian bagi pemiliknya.
Karena itu, sebelum memiliki golok Ciomas, seseorang biasanya menjalani ritual kecil: doa, sedekah, dan niat yang baik.
Hal ini dimaksudkan agar golok yang dimiliki tidak menjadi alat kesombongan, melainkan pelindung kehormatan diri dan keluarga.
Klasifikasi Golok Ciomas
Empu di Ciomas mengenal beberapa tipe golok dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
Beberapa yang paling terkenal antara lain:
- Salam Nunggal – Bilah tunggal tanpa pamor, melambangkan kesederhanaan dan keteguhan hati.
- Kembang Kacang – Memiliki lengkungan halus di pangkal bilah, sering digunakan oleh jawara silat.
- Mamancungan – Ujungnya sedikit melengkung ke atas, efektif untuk tebasan dan potongan cepat.
Setiap jenis memiliki nilai simbolik tersendiri dan biasanya dibuat sesuai karakter pemiliknya.
Proses Penyepuhan dan Gendam: Ritual Memberi “Isi” pada Bilah
Salah satu rahasia keistimewaan Golok Ciomas terletak pada proses penyepuhan.
Proses ini tidak hanya teknis, tetapi juga spiritual.
Besi dipanaskan hingga merah menyala, lalu didinginkan dalam air atau minyak dengan doa tertentu.
Ritual ini dilakukan pada waktu-waktu khusus, biasanya menjelang subuh atau malam Jumat.
Ada pula proses yang disebut gendam, yaitu pengisian energi melalui lantunan doa dan dzikir.
Empu akan meniatkan agar golok yang ditempa membawa manfaat, bukan mudarat.
Inilah sebabnya mengapa setiap Golok Ciomas dianggap memiliki “jiwa” yang berbeda, tergantung siapa yang menempanya dan untuk apa tujuannya.
Golok Ciomas bukan sekadar benda pusaka, melainkan identitas kultural masyarakat Banten.
Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada tajamnya bilah, tapi pada ketulusan niat dan keberanian menjaga kebenaran.
Golok Sulangkar: Bilah Kembar Penanda Status Sosial Para Bangsawan
Golok Sulangkar bukan sekadar senjata, tetapi juga lambang kehormatan dan kewibawaan.
Dulu, senjata ini hanya dimiliki oleh kalangan tertentu — terutama para pejabat Kesultanan Banten, bangsawan, dan ulama terkemuka.
Keberadaannya menunjukkan perbedaan status sosial sekaligus menjadi simbol kekuasaan spiritual dan politik.
Kisah di Balik Sulangkar: Senjata Eksklusif bagi Kalangan Kesultanan
Nama Sulangkar berasal dari kata dasar “sulang” yang berarti “berpasangan” dan “kar” yang berarti “besi.”
Sesuai namanya, golok ini selalu dibuat sepasang: satu disimpan di rumah sebagai pusaka, dan satu lagi dibawa saat upacara resmi atau peperangan.
Keunikan ini melambangkan keseimbangan antara kekuatan lahir dan batin, dunia dan akhirat.
Masyarakat Banten percaya, siapa pun yang memiliki Golok Sulangkar sejati harus mampu menjaga dua hal itu agar hidupnya seimbang.
Konon, Golok Sulangkar juga digunakan dalam prosesi pelantikan pejabat kerajaan.
Saat seorang bangsawan diangkat jabatan, sepasang golok diserahkan sebagai tanda bahwa ia siap menjaga rakyat dengan adil dan bijak.
Jejak Golok Sulangkar Milik Sultan Ageng Tirtayasa
Salah satu koleksi Golok Sulangkar paling terkenal diyakini milik Sultan Ageng Tirtayasa, sultan besar yang memimpin Banten pada abad ke-17.
Menurut catatan lokal dan dokumentasi museum, golok itu memiliki bilah sepanjang hampir 60 sentimeter,
dengan pamor berpola kulit semangka dan gagang dari kayu cendana berlapis perak.
Golok ini bukan hanya pusaka pribadi, tapi juga simbol perjuangan Sultan Ageng melawan dominasi VOC.
Banyak peneliti percaya bahwa Sulangkar milik beliau ditempa khusus oleh empu terbaik Ciomas,
dengan ritual yang melibatkan dzikir dan pembacaan ayat suci agar menjadi simbol kekuatan yang suci.
Perbedaan Golok Sulangkar dengan Golok Banten Lainnya
Jika dibandingkan dengan Golok Ciomas atau Bedog rakyat, Sulangkar punya ciri visual yang langsung menonjol.
Bilahnya biasanya lebih ramping, permukaannya halus, dan hiasannya sangat detail.
Beberapa bahkan memiliki inkrustasi logam mulia seperti perak atau kuningan di bagian gagang.
Selain itu, Sulangkar sering disimpan dalam sarung berlapis kain sutra atau beludru merah.
Hal ini menandakan posisinya sebagai senjata upacara, bukan untuk bertarung di medan perang.
Namun, secara teknis, bilahnya tetap sangat tajam dan seimbang.
Golok ini juga sering diberi ukiran kaligrafi Arab atau lafaz “Allah” dan “Muhammad”,
menunjukkan kedekatan antara kekuatan spiritual dan tanggung jawab moral pemiliknya.
Kisah Kolektor dan Warisan Keturunan Bangsawan
Hingga kini, masih ada keluarga di Banten yang mengaku menyimpan warisan Golok Sulangkar turun-temurun.
Salah satu di antaranya adalah keluarga keturunan ulama besar di daerah Kasemen, Serang.
Golok mereka tidak pernah diperjualbelikan — hanya diturunkan kepada anak laki-laki tertua sebagai simbol amanah keluarga.
Beberapa kolektor juga menuturkan bahwa mendapatkan Golok Sulangkar asli bukan perkara mudah.
Selain langka, mereka harus memastikan asal-usul dan legitimasi pusaka itu jelas.
Bagi para kolektor sejati, memiliki Sulangkar bukan soal prestise,
tetapi bentuk penghormatan pada sejarah dan budaya Banten yang luhur.
Golok Sulangkar menjadi bukti bahwa senjata tradisional di Banten tidak hanya berfungsi untuk bertahan hidup,
tetapi juga sebagai penanda martabat, moralitas, dan tanggung jawab sosial.
Ia mewakili nilai bahwa kekuasaan sejati bukan datang dari tajamnya bilah, melainkan dari kebijaksanaan pemegangnya.
Kujang Banten: Warisan Sunda yang Hidup di Tanah Kesultanan
Banten memang dikenal sebagai wilayah pesisir yang sibuk dan kosmopolitan sejak masa lampau.
Namun, akar budayanya masih berhubungan erat dengan tradisi Sunda Pajajaran.
Salah satu buktinya adalah keberadaan Kujang Banten, senjata khas yang bentuk dan filosofinya mirip dengan kujang dari wilayah Bogor atau Priangan,
tapi punya sentuhan spiritual dan estetika khas Banten.
Dari Pajajaran ke Banten: Perjalanan Sebuah Senjata Suci
Kujang sudah dikenal sejak abad ke-8 di wilayah Tatar Sunda.
Awalnya bukan sekadar senjata, tapi juga alat pertanian yang sakral.
Bentuknya menyerupai sabit dengan lekukan-lekukan tajam yang punya makna filosofis.
Saat pengaruh Kesultanan Banten mulai berkembang, senjata ini ikut bertransformasi.
Para empu di daerah barat Jawa memadukan bentuk kujang lama dengan sentuhan baru:
ukiran kaligrafi Arab, simbol bulan sabit, dan hiasan berbentuk bunga teratai di pangkal bilahnya.
Perpaduan ini menandai transisi budaya dari era Hindu-Sunda ke Islam Banten.
Jadi, Kujang Banten bukan sekadar hasil tempaan logam, tapi juga hasil tempaan sejarah dan keyakinan.
Ciri Khas Kujang Banten
Kujang Banten punya ciri visual yang sedikit berbeda dari kujang di daerah lain.
Bentuknya cenderung lebih langsing dan tidak terlalu banyak lekukan tajam.
Bilahnya biasanya berwarna kehitaman dengan kilau halus hasil proses tempa dan rendaman minyak kelapa.
Ujung kujang sering dibuat melengkung seperti paruh burung elang — simbol ketajaman pandangan dan kewaspadaan.
Gagangnya terbuat dari kayu jati atau gembol nangka, dibentuk menyerupai kepala naga atau burung garuda.
Yang paling unik, beberapa kujang pusaka di Banten memiliki inskripsi kaligrafi Arab kecil di bagian bilah,
biasanya berupa lafaz “Bismillah” atau “La ilaha illallah.”
Hal ini menunjukkan kuatnya nilai religius yang melekat dalam pandangan hidup masyarakat Banten kala itu.
Fungsi Simbolik: Senjata, Tanda Kebijaksanaan, dan Alat Ritual
Dalam kehidupan masyarakat Banten lama, Kujang tidak hanya berfungsi sebagai alat bela diri.
Ia juga digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan.
Misalnya, dalam tradisi ruwatan desa atau selamatan bumi, kujang disimpan di tengah ruangan sebagai simbol perlindungan spiritual.
Para ulama dan jawara yang memegang kujang dianggap memiliki keseimbangan antara ilmu lahir dan batin.
Kujang bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati adalah mengendalikan diri.
Beberapa empu bahkan menanamkan doa dan ayat suci saat menempa bilah kujang.
Proses ini dikenal dengan istilah “ngempu batin,” yaitu menajamkan bukan hanya besi,
tetapi juga niat dan keikhlasan pembuatnya agar senjata menjadi berkah, bukan kutukan.
Kujang Sebagai Identitas Budaya Banten
Kini, Kujang Banten menjadi simbol identitas daerah yang menggabungkan ketegasan dan spiritualitas.
Dalam berbagai festival budaya dan pameran kerajinan logam tradisional, kujang selalu mendapat tempat istimewa.
Para pengrajin modern bahkan menghidupkan kembali tradisi menempa kujang dengan teknik kuno,
sekaligus menambah nilai estetika agar bisa diapresiasi oleh generasi muda.
Kujang juga sering dijadikan cinderamata resmi daerah dalam kegiatan pemerintahan atau kebudayaan,
menegaskan bahwa Banten bukan hanya tanah jawara, tapi juga tanah yang menjunjung nilai-nilai luhur dan keselarasan alam.
Makna Filosofis Kujang Banten
Secara simbolik, kujang menggambarkan tiga hal penting dalam pandangan hidup masyarakat Banten:
- Keteguhan iman – diwakili oleh bentuknya yang tegak dan tajam.
- Kebijaksanaan dalam bertindak – tercermin dari lekuk halus di bilah yang tidak asal membabi buta.
- Keseimbangan dunia dan akhirat – disimbolkan lewat dua sisi tajam: satu untuk bertahan, satu untuk introspeksi.
Kujang Banten mengajarkan bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan hanyalah kesia-siaan.
Dan dalam budaya Banten, seorang jawara sejati bukan yang paling kuat,
tapi yang paling mampu menahan diri di saat marah.
Bedog dan Parang Pandeglang: Senjata Rakyat, Cermin Ketangguhan Petani Banten
Kalau Golok Sulangkar mewakili kaum bangsawan dan Kujang Banten jadi simbol spiritualitas,
maka Bedog dan Parang Pandeglang adalah wujud nyata dari kehidupan rakyat kecil yang tangguh, mandiri, dan pekerja keras.
Senjata ini lahir dari keseharian: menebas bambu, membuka hutan, atau menjaga diri saat bepergian di kebun.
Namun seiring waktu, bedog dan parang berubah menjadi lambang kemandirian dan keberanian rakyat Banten.
Asal-Usul Bedog: Dari Alat Dapur Jadi Senjata Jawara
Kata bedog berasal dari bahasa Sunda yang berarti “pisau besar” atau “golok serbaguna.”
Di Pandeglang dan Lebak, bedog digunakan untuk segala hal — mulai dari memotong kayu, menyembelih hewan,
hingga sebagai alat pertahanan diri jika ada bahaya.
Bentuknya sederhana, tapi fungsional: bilah lurus sekitar 30–40 sentimeter,
gagang kayu jati polos, dan sarungnya terbuat dari kulit atau bambu belah.
Namun di tangan para pandai besi Banten, bedog bisa menjadi karya seni dengan pamor unik,
terbuat dari lapisan baja tempa yang kuat dan elastis.
Dalam sejarah lokal, bedog juga dikaitkan dengan para jawara kampung —
para pelindung desa yang menjaga keamanan dan kehormatan warga.
Mereka tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga punya kode moral: tidak menyerang duluan,
tapi siap melindungi yang lemah bila keadilan diinjak.
Parang Pandeglang: Senjata dari Tanah Petani dan Nelayan
Berbeda dengan bedog, Parang Pandeglang punya bentuk lebih panjang dan melengkung di ujungnya.
Senjata ini berkembang di wilayah pesisir selatan Banten — seperti Carita, Sumur, dan Panimbang —
di mana masyarakatnya hidup dari hasil hutan dan laut.
Parang digunakan untuk menebas rotan, membuka jalur di kebun kelapa,
atau memotong jaring saat menangkap ikan besar di laut.
Tapi dalam kondisi genting, parang bisa berubah fungsi menjadi alat bela diri.
Para nelayan tua di Pandeglang bahkan punya pepatah:
“Parang teu meunang leungit, sabab eta nyawa urang di laut.”
Artinya, “Parang jangan sampai hilang, karena itu nyawa kita di laut.”
Ciri Visual dan Teknik Pembuatan
Parang Pandeglang biasanya lebih panjang daripada bedog, sekitar 50–60 sentimeter.
Bilahnya agak melengkung, bagian punggung tebal, dan ujungnya tajam menyerupai sabit.
Gagangnya sederhana, sering dibungkus dengan serat rotan agar tidak licin saat digunakan di ladang atau laut.
Pembuatan parang dilakukan dengan cara tempa lipat tradisional,
menggunakan arang kayu dan palu tangan tanpa mesin modern.
Empu Banten percaya bahwa logam terbaik harus “dihidupkan” dengan niat baik,
karena senjata yang dibuat dengan amarah akan membawa sial bagi pemiliknya.
Beberapa pandai besi tua di Menes dan Saketi masih menjaga tradisi ini sampai sekarang,
meski jumlahnya semakin sedikit karena masuknya parang pabrikan dari luar daerah.
Fungsi Sosial dan Filosofi Parang
Parang bagi masyarakat Pandeglang bukan hanya alat kerja.
Ia juga bagian dari identitas.
Setiap keluarga petani biasanya punya minimal satu parang pusaka yang diwariskan turun-temurun.
Biasanya digunakan saat hajat bumi atau ritual panen, sebagai simbol rasa syukur pada alam.
Selain itu, parang juga dianggap menggambarkan nilai ketekunan dan kesetiaan.
Karena meski sederhana, ia selalu ada dalam setiap aspek kehidupan rakyat —
dari membuka kebun sampai menjaga rumah tangga.
Dalam pandangan budaya lokal, seseorang yang bisa mengasah parang dengan sabar
melambangkan pribadi yang siap menghadapi kerasnya hidup dengan tenang dan teliti.
Bedog dan Parang: Dua Wajah yang Saling Melengkapi
Di Banten, bedog dan parang bukan sekadar alat potong.
Keduanya adalah simbol kerja keras rakyat dan semangat pantang menyerah.
Bedog mewakili wilayah pegunungan dan kehidupan agraris,
sementara parang melambangkan dunia pesisir yang keras dan berani.
Dua-duanya mencerminkan karakter orang Banten: kuat, sederhana, tapi berwibawa.
Dalam filosofi lokal, orang yang memegang bedog atau parang dengan bijak berarti sudah “mapan” —
karena tahu kapan harus menebas, dan kapan harus berhenti.
Badik dan Rencong Banten: Jejak Persilangan Budaya di Tanah Jawara
Banten sejak masa Kesultanan bukan cuma pusat perdagangan rempah.
Pelabuhannya di pesisir barat Jawa jadi tempat bertemunya pedagang, ulama, dan pejuang dari berbagai daerah Nusantara — termasuk Bugis, Makassar, dan Aceh.
Pertemuan budaya itu nggak cuma melahirkan hubungan dagang dan pernikahan antarbangsa,
tapi juga pertukaran pengetahuan, termasuk dalam pembuatan dan filosofi senjata.
Dari sinilah muncul dua jenis senjata unik yang akhirnya melebur dengan identitas lokal: Badik dan Rencong Banten.
Badik Banten: Dari Senjata Bugis Menjadi Simbol Keberanian Tanah Jawara
Asal-usul badik di Banten diyakini datang dari para pelaut Bugis dan Makassar
yang berlayar ke barat sejak abad ke-16 untuk berdagang di pelabuhan Banten Girang dan Karangantu.
Sebagian menetap dan menjadi pengawal Kesultanan, membawa serta senjata khas mereka: badik — belati kecil melengkung dengan ujung meruncing.
Namun, lama-lama badik ini diadaptasi oleh para empu lokal.
Bentuknya tetap mirip, tapi ada sentuhan khas Banten: bilahnya lebih tebal, pamornya lebih halus, dan sarungnya dihiasi ukiran sederhana.
Di kalangan jawara, badik digunakan bukan untuk menyerang, tapi sebagai simbol kehormatan dan kesiapsiagaan.
Seorang pendekar sejati Banten disebut belum lengkap kalau belum punya badik di pinggang —
bukan untuk gagah-gagahan, tapi sebagai pengingat agar selalu mawas diri.
Bahkan dalam beberapa kisah lisan, badik dijadikan alat sumpah persaudaraan antarjawara,
dengan ujungnya disentuhkan ke tanah dan langit sebagai simbol kesetiaan pada kebenaran.
Rencong Banten: Pengaruh Aceh di Tanah Kesultanan
Rencong, yang dikenal sebagai senjata khas Aceh, juga pernah menjejak di Banten.
Kedekatan politik dan hubungan dakwah antara ulama Banten dan Aceh membuat pertukaran budaya ini sangat mungkin.
Para ulama Aceh yang datang ke Banten pada abad ke-17 membawa rencong bukan sekadar sebagai senjata,
tapi juga simbol spiritualitas dan keberanian dalam membela agama.
Empu Banten kemudian meniru bentuknya, namun memodifikasi ukuran dan lekukan bilahnya.
Rencong Banten cenderung lebih kecil, gagangnya melengkung lembut, dan sarungnya kadang dibungkus kain putih — menandakan kesucian niat.
Di kalangan santri-jawara (pendekar yang juga belajar agama), rencong dianggap lambang keseimbangan antara ilmu dan iman.
Senjata ini jarang digunakan untuk bertarung, tapi sering disimpan sebagai pusaka doa, dipercaya melindungi pemiliknya dari bahaya.
Jejak Arkeologis dan Catatan Tertulis
Peneliti dari Balai Arkeologi Jawa Barat pernah menemukan fragmen bilah menyerupai badik di wilayah Caringin dan Ciomas.
Beberapa di antaranya menunjukkan pola pamor spiral yang mirip dengan logam Sulawesi.
Hal ini memperkuat teori bahwa Banten adalah simpul penting dalam penyebaran teknologi tempa logam antarwilayah.
Sementara dalam Sajarah Banten (naskah abad ke-17), disebutkan tentang “bilah kecil bersarung putih milik ulama dari utara”
yang kemungkinan besar mengacu pada rencong.
Catatan ini memperlihatkan bahwa senjata bukan hanya alat perang, tapi juga media simbolik pertukaran budaya dan spiritualitas.
Filosofi di Balik Dua Bilah
Baik badik maupun rencong sama-sama menanamkan nilai sadar diri dan kendali amarah.
Bentuk bilahnya yang ramping dan tajam mencerminkan prinsip “kecil tapi mematikan,”
menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dari ukuran, tapi dari ketepatan dan tujuan penggunaannya.
Dalam pandangan masyarakat Banten, memiliki badik atau rencong bukan soal status,
tapi tentang kedewasaan batin dan kesanggupan menjaga kehormatan.
Maka tak heran kalau dua senjata ini sering diwariskan kepada murid atau anak tertua
sebagai simbol tanggung jawab moral, bukan sekadar benda pusaka.
Badik dan rencong membuktikan bahwa Banten bukan budaya yang tertutup.
Ia mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati dirinya —
menjadikan setiap bilah senjata bukan hanya alat, tapi saksi sejarah percampuran peradaban.
Di Balik Bilah: Filosofi Pamor dan Desain Gagang Senjata Banten
Bagi orang Banten, senjata bukan cuma logam yang ditempa jadi tajam.
Ia dianggap punya “isi” — bukan dalam arti gaib yang menakutkan,
tapi kekuatan batin hasil doa, niat, dan energi spiritual sang empu.
Karena itu, setiap bagian dari senjata — dari bilah, pamor, hingga gagangnya —
memiliki makna simbolik yang mencerminkan pandangan hidup orang Banten:
keseimbangan antara tenaga, cipta, dan rasa.
Pamor: Lukisan Doa di Atas Besi
“Pamor” adalah pola yang muncul di permukaan bilah setelah proses penempaan logam berpamor (biasanya campuran nikel, besi, dan baja).
Tapi bagi masyarakat Banten, pamor bukan sekadar estetika.
Setiap pola diyakini menyimpan doa dan harapan.
Contohnya:
- Pamor Beras Wutah melambangkan rezeki yang mengalir tanpa henti — cocok bagi petani atau pedagang.
- Pamor Udan Mas (hujan emas) menggambarkan kemakmuran dan keberuntungan.
- Pamor Kulit Semangka dipercaya memberi perlindungan dari niat jahat dan bala.
Para empu tidak membuat pamor sembarangan.
Sebelum menempa, mereka melakukan ritual puasa dan meditasi untuk “menyatu” dengan logam yang akan dibentuk.
Dalam tradisi Ciomas, proses ini disebut “ngaji besi” — membaca doa-doa saat logam dipanaskan agar hasilnya membawa berkah.
Gagang (Hulu): Simbol Kendali dan Kebijaksanaan
Kalau bilah mewakili tenaga dan keberanian, maka gagang adalah lambang kendali dan kebijaksanaan.
Desain gagang senjata Banten punya makna mendalam dan penuh detail.
Ukiran berbentuk manusia berlutut menandakan ketundukan kepada Tuhan.
Motif hewan seperti macan atau naga melambangkan kekuatan dan penjaga diri.
Sementara bentuk flora — seperti bunga melati atau daun sulur — menandakan kehalusan budi dan cinta kasih.
Gagang sering dibuat dari bahan yang memiliki nilai spiritual:
tanduk kerbau, kayu kemuning, atau bahkan gading.
Pemilihan bahan tidak asal, karena dipercaya memengaruhi “energi” senjata.
Tanduk kerbau misalnya, melambangkan keteguhan, sedangkan kayu kemuning dipercaya membawa ketenangan.
Sarung (Warangka): Rasa, Penutup, dan Kesopanan
Dalam filosofi Banten, sarung bukan sekadar pelindung bilah.
Ia adalah simbol “rasa” — pengendali dari keberanian agar tidak berubah menjadi kekerasan.
Senjata yang baik bukan yang selalu ditarik, tapi yang tahu kapan harus disarungkan.
Karena itu, warangka dibuat dengan penuh perhatian.
Bentuknya sederhana tapi proporsional, sering dihias ukiran halus atau dibungkus kain.
Bagi para jawara, cara menyarungkan senjata mencerminkan karakter seseorang.
Orang yang menyarungkan bilah dengan tenang dianggap punya jiwa matang dan rendah hati.
Keseimbangan Kosmologis: Isi, Cipta, dan Rasa
Filosofi senjata Banten berpijak pada prinsip keseimbangan kosmologis.
Tiga elemen utama — bilah (isi), gagang (cipta), dan sarung (rasa) —
melambangkan kesatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa manusia.
Orang yang mampu menjaga keseimbangan itu dianggap sebagai “manusa sampurna”,
yakni pribadi yang mampu mengendalikan kekuatan tanpa kehilangan nurani.
Dalam konteks sosial, prinsip ini juga jadi panduan etika para jawara.
Mereka diajarkan untuk tidak sombong atas kekuatan,
tidak cepat menghunus senjata,
dan selalu menempatkan keberanian dalam bingkai moral.
Pandangan Empu Ciomas
Salah satu empu tua di Ciomas pernah berkata:
“Senjata itu seperti manusia. Kalau ditempa dengan sabar dan doa,
ia akan jadi pelindung. Tapi kalau dibuat dengan amarah,
ia akan jadi kutukan.”
Kata-kata itu mencerminkan kearifan lokal yang masih dipegang hingga kini.
Bahwa inti dari sebuah senjata bukan pada ketajaman bilahnya,
tapi pada kemurnian niat sang pembuat dan pemiliknya.
Dengan memahami filosofi ini, kita bisa melihat bahwa senjata tradisional Banten bukan sekadar benda logam,
tapi cermin dari peradaban spiritual yang matang.
Ia mengajarkan bagaimana kekuatan sejati justru lahir dari keseimbangan antara tenaga dan kebijaksanaan.
Proses Penempaan Sakral: Kunjungan ke Pusat Pembuatan Senjata Tradisional Ciomas
Kalau bicara senjata tradisional Banten, nama Ciomas hampir selalu disebut pertama.
Wilayah yang berada di kaki Gunung Karang, Kabupaten Serang, ini dikenal sebagai tanah para empu —
tempat lahirnya golok legendaris seperti Golok Ciomas, Golok Kembang Kacang, dan Salam Nunggal.
Di sini, pekerjaan menempa logam bukan sekadar profesi, tapi warisan suci.
Setiap palu yang diketukkan, setiap bara yang menyala, adalah bagian dari ritual yang dijaga ratusan tahun lamanya.
Menyusuri Bengkel Empu
Begitu memasuki bengkel empu di Ciomas, suasananya langsung terasa berbeda.
Tidak ada mesin modern, hanya tungku arang, palu besi, dan hawa panas yang menyengat.
Namun di balik kesederhanaannya, tempat itu menyimpan kedisiplinan spiritual yang luar biasa.
Sebelum memulai pekerjaan, empu biasanya membaca doa dan menyalakan dupa.
Mereka percaya logam punya “roh” yang harus diperlakukan dengan hormat.
Besi tidak boleh dipukul sembarangan, apalagi dengan emosi —
karena bisa membuat bilahnya “mati” atau tidak memiliki isi.
Wawancara dengan Empu Ciomas
Seorang empu tua, dikenal sebagai Empu H. Marjuki, bercerita:
“Kami tidak sekadar membuat senjata. Kami membentuk watak besi.
Besi itu harus nurut pada niat baik. Kalau niatnya sombong, hasilnya pasti jelek.”
Empu Marjuki adalah generasi keempat dari keluarganya yang mengabdi sebagai pandai besi.
Ia masih menggunakan metode yang sama dengan leluhurnya: memanaskan besi hingga merah membara,
lalu menempanya berulang-ulang sambil membaca doa.
Ia bilang, proses ini bisa memakan waktu tiga sampai tujuh hari tergantung jenis senjatanya.
Bukan karena sulit, tapi karena setiap tahap harus dilakukan dengan kesabaran dan konsentrasi penuh.
Proses Penempaan Langkah Demi Langkah
- Pemilihan Logam
Empu hanya menggunakan besi tua, terutama dari pegas mobil atau rel kereta.
Alasannya, logam tua dianggap lebih matang dan “berjiwa kuat.” - Pembakaran dan Penempaan Awal
Besi dipanaskan di tungku arang hingga membara.
Lalu dipukul berulang kali untuk mengeluarkan kotoran dan membentuk pola dasar bilah. - Lipatan (Laminasi)
Logam dilipat dan ditempa berkali-kali untuk memperkuat struktur serta menciptakan pamor alami.
Setiap lipatan diiringi dengan bacaan doa — simbol penyatuan tenaga dan spiritualitas. - Penyepuhan (Pendinginan Sakral)
Setelah bentuknya sempurna, bilah dicelupkan ke air khusus.
Air ini tidak sembarangan, biasanya diambil dari tujuh sumber mata air sekitar Ciomas yang dianggap suci. - Pengasahan dan Penyematan Gagang
Setelah bilah selesai, empu menajamkannya secara manual dan memasang gagang dari kayu pilihan.
Proses ini juga diiringi doa, karena diyakini saat inilah “jiwa” senjata mulai menyatu dengan bentuk fisiknya.
Ritual dan Pantangan
Selama proses penempaan, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar:
- Tidak boleh menempa saat marah atau dalam keadaan kotor hati.
- Tidak boleh makan daging tertentu (biasanya sapi) selama proses berlangsung.
- Tidak boleh membicarakan hal kotor atau kasar di sekitar tungku.
Bagi para empu, ini bukan sekadar kepercayaan kuno, tapi kode etik kerja spiritual.
Mereka percaya, logam menyerap energi di sekitarnya.
Jadi, kalau suasana bengkel kotor atau negatif, hasilnya pun akan “kosong.”
Galeri Foto dan Dokumentasi
Banyak peneliti budaya dan fotografer dokumenter yang datang ke Ciomas untuk merekam tradisi ini.
Foto-foto mereka menampilkan suasana yang magis:
bara api yang menyala di tengah gelap, percikan logam beterbangan, dan empu tua yang memukul besi dengan ritme teratur seperti meditasi.
Beberapa museum di Banten dan Jakarta bahkan menyimpan dokumentasi proses tempa ini sebagai warisan budaya tak benda.
Karena meskipun zaman berubah, tradisi ini masih bertahan —
jadi bukti bahwa kearifan lokal bisa hidup berdampingan dengan modernitas.
Makna di Balik Proses
Proses tempa di Ciomas bukan cuma tentang menciptakan benda tajam.
Ia adalah metafora kehidupan.
Besi yang keras dilembutkan oleh api, lalu dipukul agar menjadi kuat tapi lentur.
Begitu juga manusia: diuji oleh kesulitan agar tidak patah, tapi tangguh.
Di akhir proses, empu akan mengucap kalimat sederhana:
“Alhamdulillah, lahir sudah anak besi.”
Bagi mereka, setiap bilah adalah “anak spiritual” yang lahir dari kerja, doa, dan niat suci.
Karena itu, senjata dari Ciomas tak hanya tajam di permukaan — tapi juga punya ruh yang menenangkan.
Panduan Kolektor: Cara Membedakan Pusaka Asli dan Palsu serta Etika Kepemilikan
Banten dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan tradisi pembuatan senjata yang masih hidup.
Dari golok Ciomas, kujang Banten, sampai badik Serang — semuanya punya nilai budaya sekaligus nilai koleksi yang tinggi.
Tapi di sisi lain, banyak juga barang tiruan yang beredar di pasar antik atau toko oleh-oleh, sering kali mengatasnamakan “pusaka asli Banten”.
Nah, biar gak ketipu, berikut panduan detail buat mengenali pusaka asli, sekaligus cara menghormati warisannya.
1. Kenali Ciri Fisik Senjata Asli Banten
a. Tekstur dan Warna Logam
Besi pusaka asli hasil tempa tradisional tidak pernah halus sempurna.
Selalu ada sedikit “urat” atau pola lipatan di permukaannya — hasil dari proses tempa berulang.
Warna bilahnya juga cenderung keabu-abuan doff (bukan mengilap seperti stainless steel).
b. Pamor atau Serat
Kalau kamu lihat pamor seperti gelombang halus atau motif samar di bilah, itu bukan corak buatan mesin.
Itu hasil lipatan logam yang terbentuk alami saat proses tempa dan penyepuhan.
Setiap empu punya “tanda tangan” pamornya sendiri, jadi hampir tidak ada dua bilah yang identik.
c. Gagang dan Sarung
Golok asli Banten biasanya memakai kayu lokal keras seperti kayu jati, waru, atau trembesi.
Gagangnya sering dihiasi ukiran sederhana tapi punya filosofi:
misalnya motif kembang kacang melambangkan keindahan dalam ketegasan.
Sarung (warangka)-nya biasanya dibungkus kulit atau kayu dengan bentuk ergonomis, bukan dekorasi berlebihan.
d. Berat dan Keseimbangan
Golok tradisional terasa padat tapi seimbang di tangan.
Kalau kamu pegang dan terasa “kosong” atau terlalu ringan, kemungkinan besar itu tiruan aluminium atau cetakan industri.
2. Ciri Non-Fisik: Energi dan Riwayat
Empu di Ciomas percaya, setiap bilah punya “isi” — bukan mistik semata, tapi hasil dari niat dan disiplin spiritual selama penempaan.
Banyak kolektor berpengalaman bilang, pusaka asli terasa “adem” atau punya aura tenang saat dipegang, bukan seram.
Kalau kamu beli dari empu atau pewaris yang jelas silsilahnya, biasanya mereka juga akan menceritakan:
- Tahun pembuatan,
- Siapa empunya,
- Untuk tujuan apa dibuat (pekerjaan, perlindungan, simbol adat).
Barang palsu umumnya tidak punya storyline seperti ini — hanya dijual pakai label “asli Banten” tanpa konteks.
3. Waspadai Pusaka Replika dan “Isi-Iisian”
Pasar online dan pameran budaya kadang menjual replika yang disebut “pusaka aktif”.
Banyak di antaranya cuma produk komersial yang disiram minyak, dibacakan doa singkat, lalu dijual mahal.
Secara budaya, itu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan simbol leluhur.
Karena empu sejati tidak pernah menjual pusaka secara massal atau untuk tujuan komersial murni.
Kalau kamu hanya ingin punya replika dekoratif, gak masalah.
Tapi jangan menyebutnya “pusaka asli Ciomas” kecuali memang dibuat oleh empu dari wilayah tersebut dan diakui oleh komunitasnya.
4. Etika Kepemilikan Pusaka
Memiliki senjata tradisional bukan cuma soal koleksi atau estetika.
Ada tanggung jawab moral dan budaya yang menyertainya.
Berikut etika yang disepakati oleh para empu dan pelestari budaya Banten:
a. Hormati Asal-Usulnya
Selalu sebut nama empu atau daerah asalnya saat menampilkan pusaka.
Itu bentuk penghargaan kepada leluhur yang menciptakannya.
b. Jangan Dipamerkan Sembarangan
Pusaka bukan aksesori.
Mengunggahnya ke media sosial tanpa konteks budaya bisa menimbulkan kesalahpahaman atau kesan mistik berlebihan.
c. Rawat dengan Benar
Gunakan minyak khusus (biasanya minyak kelapa murni atau minyak cendana) untuk menjaga bilah tetap awet.
Simpan di tempat kering, jauh dari bahan kimia atau kelembapan tinggi.
d. Jangan Gunakan untuk Kekerasan
Golok dan senjata tradisional Banten diciptakan bukan untuk berperang, tapi untuk simbol kehormatan dan perlindungan.
Menggunakannya untuk menakuti orang atau kejahatan sama saja mencederai maknanya.
e. Jangan Perjualbelikan Secara Ilegal
Pusaka yang berusia ratusan tahun masuk kategori warisan budaya tak benda.
Menjualnya tanpa izin atau keluar negeri tanpa sertifikat resmi bisa melanggar hukum warisan budaya nasional.
5. Tips Membeli Secara Aman
Kalau kamu tertarik membeli senjata tradisional Banten, lakukan langkah ini:
- Datangi komunitas resmi empu Ciomas atau forum budaya Banten.
- Minta surat keterangan dari pembuatnya.
- Hindari transaksi online tanpa dokumentasi visual atau asal-usul jelas.
- Tanyakan bahan, tahun pembuatan, dan teknik tempa yang digunakan.
Lebih baik membeli satu bilah yang benar-benar autentik daripada sepuluh replika yang tidak punya nilai budaya.
6. Penegasan Nilai Budaya
Pusaka Banten bukan sekadar benda warisan.
Ia adalah jejak sejarah, spiritualitas, dan seni tempa yang menyatu dalam satu bentuk.
Setiap garis di bilahnya adalah simbol ketekunan dan doa para empu.
Karena itu, memiliki atau mempelajarinya berarti ikut menjaga identitas Banten itu sendiri.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Senjata Tradisional Banten
1. Di mana saya bisa melihat koleksi senjata tradisional Banten yang asli?
Koleksi senjata tradisional Banten bisa kamu lihat di Museum Negeri Banten di Kota Serang.
Selain itu, beberapa kolektor pribadi dan komunitas budaya di Ciomas dan Pandeglang juga masih menyimpan pusaka lama seperti Golok Ciomas dan Golok Sulangkar.
Kalau mau pengalaman langsung, kamu bisa datang saat Festival Budaya Banten — biasanya ada pameran golok dan pertunjukan pencak silat.
2. Apakah Golok Ciomas masih dibuat hingga sekarang?
Ya, masih.
Golok Ciomas tetap ditempa oleh empu tradisional di Desa Ciomas, Kabupaten Serang.
Teknik pembuatannya diwariskan secara turun-temurun dan tetap menjaga unsur spiritual, seperti ritual penyepuhan dan doa sebelum proses tempa dimulai.
Bedanya, sekarang golok lebih banyak dibuat untuk koleksi dan upacara adat, bukan untuk bertarung.
3. Apa senjata Banten yang paling sakti menurut cerita rakyat?
Menurut kisah masyarakat, Golok Ciomas dan Kujang Banten dianggap memiliki tuah paling tinggi.
Keduanya dipercaya memiliki “isi” atau energi spiritual hasil doa dan laku tirakat sang empu.
Namun, dalam pandangan budaya modern, “kesaktian” itu lebih dimaknai sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuatan moral, bukan kekuatan gaib.
4. Bolehkah senjata pusaka Banten dimiliki oleh orang biasa?
Boleh, asal sesuai aturan.
Secara hukum, senjata tajam tradisional seperti golok boleh dimiliki untuk keperluan budaya, koleksi, atau pusaka keluarga — bukan untuk senjata fungsional.
Kamu disarankan menyimpannya di rumah dengan aman dan tidak dibawa ke tempat umum tanpa izin.
Etikanya, kalau senjata itu peninggalan keluarga, sebaiknya dijaga dan tidak dijual sembarangan.
5. Bagaimana cara belajar tentang senjata tradisional Banten lebih dalam?
Ada beberapa cara.
Pertama, kamu bisa membaca literatur sejarah dan katalog museum tentang budaya Banten.
Kedua, bergabung dengan komunitas pelestari budaya atau perguruan silat tradisional, karena mereka sering membahas filosofi dan fungsi senjata tradisional.
Ketiga, kalau kamu ingin memahami tekniknya, beberapa empu di Ciomas membuka lokakarya pandai besi tradisional, tempat kamu bisa belajar langsung proses penempaan.
6. Apakah senjata tradisional Banten diakui sebagai warisan budaya Indonesia?
Ya, benar.
Beberapa jenis senjata tradisional seperti Golok Ciomas sudah masuk dalam kategori Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pengakuan ini menegaskan bahwa golok bukan hanya benda, tetapi identitas budaya dan teknologi tradisional yang perlu dilestarikan.
7. Mengapa senjata tradisional Banten begitu terkenal dibanding daerah lain?
Karena Banten punya sejarah panjang tentang jawara, kesultanan, dan perlawanan terhadap penjajah.
Senjata di Banten bukan sekadar alat perang, tapi juga simbol keberanian, kehormatan, dan spiritualitas.
Selain itu, teknik tempa dan pamor goloknya dianggap salah satu yang paling halus dan kuat di Nusantara.
Senjata tradisional Banten bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga cermin jati diri masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, kerja keras, dan kearifan lokal.
Penutup: Warisan Pandai Besi Banten di Era Modern
Di tengah gempuran teknologi dan budaya instan, senjata tradisional Banten berdiri sebagai saksi keteguhan nilai lama.
Ia mengingatkan kita bahwa ketajaman sejati tidak lahir dari logam,
melainkan dari ketekunan, doa, dan kearifan.
Para empu di Ciomas, Serang, dan Pandeglang masih menjaga bara itu.
Dengan tungku sederhana, palu, dan napas panjang, mereka menempa bukan hanya besi —
tetapi juga karakter dan spiritualitas yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Kini, banyak anak muda mulai kembali melirik seni tempa Banten.
Bukan semata karena nilai antik, tapi karena kesadaran bahwa di balik bilah-bilah itu tersimpan filosofi hidup yang dalam:
tentang keseimbangan antara kuasa dan kebajikan.
Dari Alat Bertarung Menjadi Simbol Identitas
Dulu, golok dan kujang digunakan untuk bertahan hidup — menebas semak, menjaga kampung, atau berperang melawan penjajah.
Sekarang, fungsinya bergeser menjadi simbol identitas dan kebanggaan budaya.
Bagi masyarakat Banten, memiliki atau mempelajari senjata tradisional bukan sekadar nostalgia,
melainkan cara menghormati asal-usul dan memahami nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kesabaran, dan kehormatan.
Golok Ciomas, misalnya, kini lebih sering tampil dalam upacara adat, pameran budaya, dan penelitian antropologis.
Ia bukan lagi senjata, tapi artefak hidup yang membawa pesan damai dan kebijaksanaan.
Tantangan Pelestarian di Masa Kini
Meski jumlah empu menurun, harapan belum padam.
Pemerintah daerah, komunitas budaya, dan lembaga pendidikan mulai mengadakan program pelatihan, dokumentasi, dan pameran senjata tradisional.
Tujuannya sederhana tapi penting:
agar generasi muda tahu bahwa warisan logam ini bukan barang mistik,
melainkan capaian teknologi dan seni tinggi milik leluhur mereka.
Di beberapa kampung seperti Ciomas, masih bisa ditemui ritual penempaan sakral setiap tahun.
Acara itu bukan sekadar tradisi, tapi juga bentuk perlawanan terhadap lupa.
Sebuah pengingat bahwa Banten bukan hanya daerah dengan sejarah perjuangan,
tapi juga pusat kebudayaan logam yang membentuk jati diri masyarakatnya.
Refleksi: Menempa Diri Seperti Menempa Besi
Warisan empu Banten mengajarkan filosofi sederhana tapi abadi:
besi ditempa dengan panas, manusia ditempa oleh kehidupan.
Setiap pukulan palu, setiap lipatan bilah, melambangkan proses pembentukan diri —
dari keras menjadi lentur, dari mentah menjadi matang.
Maka, menghargai senjata tradisional bukan berarti memuja benda lamanya,
tapi meneladani nilai-nilai pembentukannya: kerja keras, disiplin, kesabaran, dan rasa hormat kepada alam dan sesama.
Penegasan Akhir
Senjata tradisional Banten adalah perpaduan antara seni, sejarah, dan spiritualitas.
Ia lahir dari tangan empu yang bekerja dengan hati, bukan mesin.
Ia menyatukan kekuatan dan kebijaksanaan, sekaligus menegaskan bahwa budaya lokal punya nilai universal —
yaitu bagaimana manusia bisa kuat tanpa kehilangan nurani.
Selama bara pandai besi di Ciomas masih menyala,
selama anak muda Banten masih mau belajar tentang leluhurnya,
maka warisan ini tidak akan punah.
Ia hanya berubah wujud — dari senjata di medan laga,
menjadi cermin jati diri dan kebanggaan budaya Banten.
Artikel ini merupakan bentuk penghormatan terhadap para empu dan pewaris tradisi tempa di Banten — mereka yang menjaga bara warisan agar tetap hidup di tengah zaman yang serba cepat.